
Saat ini, peran kartu pos memang sudah tergeser oleh media digital. Orang tidak lagi mengirim jawaban kuis ke koran atau majalah menggunakan kartu pos. Aplikasi obrolan yang memungkinkan mengirim file gambar, dokumen, maupun video telah menyingkirkan kartu pos. Belum lagi, sekarang banyak sekali jajaran aplikasi media sosial yang mengutamakan tangkapan citra. Tapi demikian, Scott Merrillees menghadirkan kenangan tentang kartu pos jauh ke belakang dalam buku terbarunya, Faces of Indonesia: 500 Postcards 1900-1945.
Kekhasan yang dimiliki oleh kartu pos sebagai media komunikasi adalah ukurannya yang ringkas. Inilah yang melatarbelakangi kelahiran kartu pos. Dus, di negeri Austria-Hungaria tersebutlah Emanuel Alexander Herrmann (1839—1902), seorang ekonom yang mengajar di Institut Teknologi Wina. Herrmann pada 26 Januari 1869 menulis artikel dan dimuat dalam surat kabar kenamaan Austria pada waktu itu, Neue Freie Presse. Dalam tulisannya, Herrmann mengemukakan bahwa waktu dan usaha yang digunakan untuk menulis surat tidak sebanding dengan ukuran dari pesan yang dikirim. Ia lalu menganjurkan metode lain yang lebih praktis dan murah untuk berkomunikasi dengan lebih sangkil dan mangkus.
Judul: The Moment of Lift: EmpowerFaces of Indonesia: 500 Postcards 1900—1945
Penulis: Scott Merrillees
ISBN: 9781529005516
Tahun : 2021
Halaman : 360 hlm.
Merekam perubahan
Gagasan Herrmann rupanya ditanggapi serius oleh Austrian Post yang kemudian menerbitkan Correspondenz-Karte pada 1 Oktober 1869. Bentuk fisik kartu pos pertama tersebut adalah kertas persegi panjang ukuran 8,5 cm x 12 cm berwarna coklat muda. Di satu sisi, terdapat ruang untuk alamat dan di sisi lain ada ruang untuk menuliskan pesan singkat. Sejak saat itulah kartu pos menjadi media komunikasi yang ringkas sekaligus populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang kala itu masih merupakan wilayah Hindia Belanda. Pos Hindia Belanda sendiri pertama kali menerbitkan kartu pos pada 1874, mengikuti penerbitan kartu pos di Belanda untuk pertama kalinya pada 1871. Kartu pos seringkali digunakan untuk menggambarkan landskap suatu kota. Maka dari itu, kartu pos sering kali dijadikan suvenir untuk para pelancong.
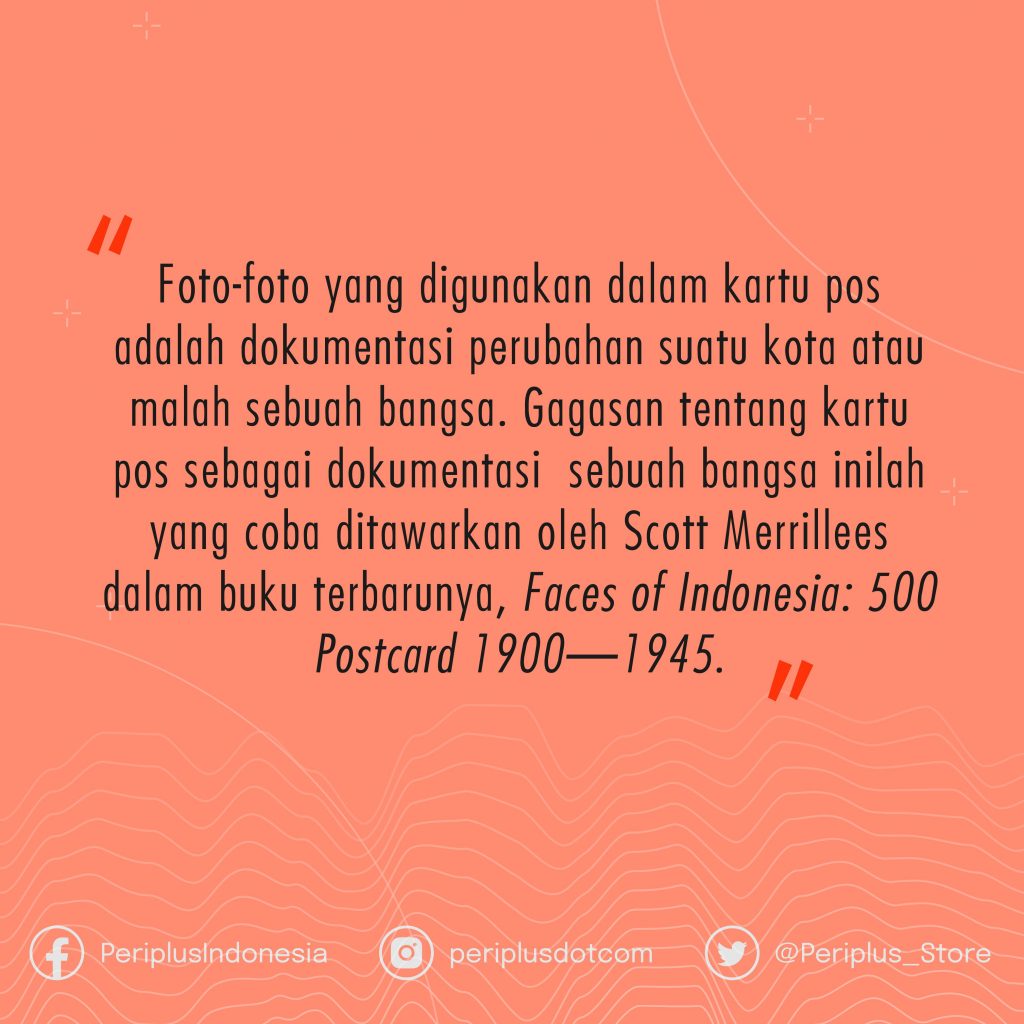
Salah satu fungsi laten kartu pos adalah kemampuannya merekam perubahan. Hal ini sangat terlihat, utamanya, jika dalam kartu pos tersebut terdapat foto. Foto-foto yang digunakan dalam kartu pos adalah dokumentasi perubahan suatu kota atau malah sebuah bangsa. Gagasan tentang kartu pos sebagai dokumentasi sebuah bangsa inilah yang coba ditawarkan oleh Scott Merrillees dalam buku terbarunya, Faces of Indonesia: 500 Postcard 1900—1945.
Ekspresi cinta
Scott, dalam Faces of Indonesia, mencoba sekali lagi mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia—mengingat tiga buku sebelumnya juga masih terkait dengan sejarah Indonesia. Dalam pengantar Faces of Indonesia, Scott sendiri menulis bahwa “[s]asaran buku ini adalah menyoroti keberagaman yang luar biasa dalam masyarakat Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan bahkan sebelum gagasan tentang bangsa ‘Indonesia’ diperbincangkan secara luas atau dipahami oleh orang-orang di luar elit politik maupun lingkaran cendekiawan [….] Keragaman yang termuat di dalam buku ini barangkali tidak lagi mudah untuk dijumpai pada masa kini, namun [keragaman inilah] yang memberikan dasar yang pasti untuk mengerti pilihan semboyan nasional ‘Bineka Tunggal Ika’ atau ‘Persatuan dalam Keberagaman.’” (hlm. 9)
Ambil satu contoh untuk menampilkan keragaman budaya Indonesia pada masa itu, misalnya pada suku bangsa Aceh. Scott menampilkan kartu pos dengan foto Tjoet Poetroe (kartu pos 1) yang merupakan salah satu istri Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah. Kartu pos tersebut diterbitkan oleh J.F.A Vlaanderen di Amsterdam sekitar 1903. Pada kartu pos nomor 2, terdapat foto Toeankoe Brahim. Pada kartu pos tersebut, dibubuhkan keterangan: “Putra Mahkota dari Aceh.” Rupanya Tjoet Poetroe dan Ibrahim mengalami peristiwa mencekam. Mereka pernah diculik oleh pasukan Belanda pada November 1902. Penculikan itu dilakukan sebagai rencana untuk memaksa Sultan menyerah. Sultan akhirnya menyerah pada 1903 dan ini menjadi tanda berakhirnya Perang Aceh. Meskipun secara resmi Perang Aceh sudah berakhir, namun gerilyawan Aceh masih melakukan serangan sporadis terhadap pasukan Belanda hingga beberapa tahun sesudahnya. Orang-orang Aceh sungguh dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan memiliki keterampilan berperang. Kartu pos nomor 13 dan 14, misalnya, menggambarkan rupa pasukan gerilyawan Aceh. (hlm. 13)
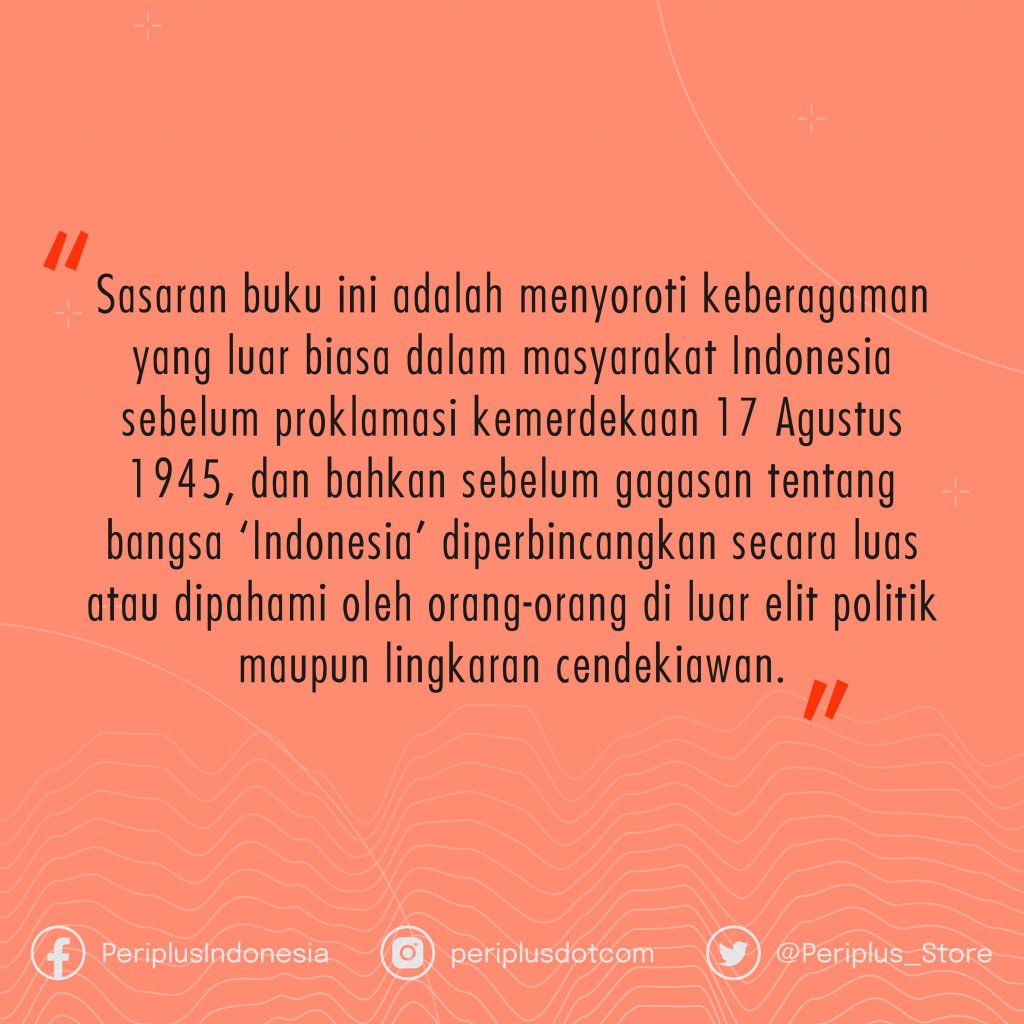
Potret keberagaman
Keragaman bangsa Indonesia dalam buku ini juga bisa dilacak dari kisah tentang kota Medan. Medan pada masa Kolonial Belanda adalah kota yang dilingkupi perkebunan. Perekenomian Medan juga berkembang pesat karena pengaruh perkebunan yang mengelilinginya. Konsekuensi lain dari kondisi seperti ini adalah keragaman etnis yang kemudian mewarnai kota Medan. Bahkan sejak akhir abad XIX, para pekerja perkebunan di Medan didatangkan ke wilayah Sumatra Utara dari India, khususnya orang-orang Keling, Bengali, atau Chetty.
Foto-foto orang-orang ini dapat dilihat pada kartu pos nomor 57—60. Selain orang-orang dari India, ada pula orang-orang dari Tiongkok, sebagaimana kartu pos nomor 53—56. Majalah National Geographic pada 1920 mendeskripsikan Medan sebagai “kota dengan beragam ras campuran” dengan menulis: “kemakmuran Medan dan posisi pentingnya disebabkan oleh lokasinya yang berada di tengah perkebunan tembakau yang kaya; konsekuensinya adalah permintaan tenaga kerja dan mengingat jarangnya penduduk asli Sumatra, populasi penduduk sebesar 14.000 jiwa mencerminkan keberagaman.” (hlm. 20)
Komunitas terbayang
Mencermati kartu pos demi kartu pos yang disajikan Scott, saya teringat gagasan Benedict Anderson tentang komunitas terbayang (imagined society). Om Ben—demikian beliau sering disapa—mengungkapkan mengapa bangsa seperti Indonesia bisa dikatakan sebagai komunitas terbayang, sebab anggota bangsa yang paling kecil sekalipun tidak akan pernah mengenal, bertemu, bahkan mendengar tentang sebagian besar anggota lain. Namun demikian, setiap bangsa tersebut, baik besar maupun kecil, terbayang di benak mereka tentang persekutuan hidup bersama. (Anderson, 2006: 6) Oleh foto-foto dalam kartu pos yang dikumpulkan oleh Scott, selain keberagaman, imajinasi kebangsaan hendak ditawarkan.

Achmad Sunjayadi dalam penelitiannya menyebut bahwa foto-foto (tentunya termasuk di dalamnya kartu pos bergambar) tentang keadaan Hindia Belanda pada awal abad XX ini merangsang pertumbuhan imaji kebangsaan di kalangan neo-priyayi yang mengenyam pendidikan di Belanda. Anak-anak muda dari golongan neo-priyayi inilah yang pada perkembangannya menyebarkan “wabah” nasionalisme dan menjadi para bapak pendiri Bangsa Indonesia. (Sunjayadi, 2008: 313) Lima ratus kartu pos yang ditampilkan dalam Faces of Indonesia menggambarkan keragaman suku bangsa di Indonesia.
Tentu saja, kehadiran buku ini diharapkan mampu merangsang kembali imaji kebangsaan Indonesia yang didasarkan pada keberagaman budaya. Namun demikian, rasanya perlu menimbang pula lakuna yang disisakan oleh buku ini. Saya akan menyebut sebagian kecil saja. Scott tidak menyertakan konteks besar terbitnya kartu pos yang menampilkan ragam wajah budaya Hindia Belanda ini. Susie Protschy menyebut bahwa foto-foto yang menggambarkan situasi Hindia Belanda pada akhir abad XIX hingga awal abad XX tidak lepas dari gagasan tentang politik etis. (Protschy, 2015:12)
Dalam kerangka pemikiran tersebut, Sunjayadi menyebut bahwa kartu pos yang dilengkapi foto suku-suku bangsa di wilayah Hindia Belanda sekadar memuaskan “fantasi kolonial” orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa pada saat itu memandang wilayah Hindia Belanda tidak lebih sebagai “surga tropik” milik Belanda. Oleh karenanya, pemerintah Hindia Belanda hendak meyakinkan calon-calon turis bahwa wilayah Hindia Belanda aman dan bersahabat untuk dikunjungi. (Sunjayadi, 2008:311)
Tulisan ini pernah dipublikasikan juga di akun Kumparan milik Periplus Bookstore Official.
Temukan pula Selisik Buku yang lain di sini.




Terima kasih sudah memberi info yang sangat menarik ini