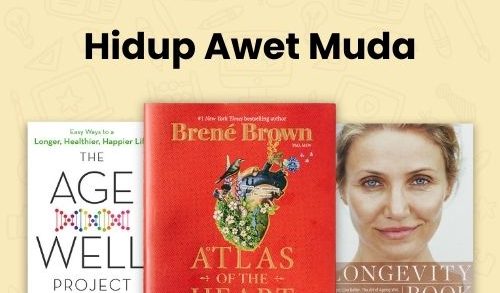IL:
Di belakang, kita bicara juga tentang kehidupan penulis. Mas Heru ini akan tampil juga dalam podcast Endgame. Satu bocoran, sebelum ditayangkan, Anda bicara bahwa menulis adalah menulis mengasah pikiran dan menulis adalah seni. Bisa dijelaskan lebih lanjut?
HL:
Misalnya, karya Leonardo da Vinci, Monalisa. Dalam lukisan perempuan itu, da Vinci memainkan horizon di belakang untuk menambah unsur kedalaman (depth), terus di senyumnya ada teknik sfumato, sehingga bentuk bibirnya dibuat tidak jelas. Akibatnya, orang ada yang bilang kalau Monalisa sedang tersenyum, namun ada juga orang yang melihat Monalisa bersedih. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Leonardo da Vinci bermain dengan otak kita, cara kita berpikir.
Akhirnya, kita bisa memberikan interpretasi pada lukisan. Itulah yang namanya seni. Dalam menulis, ada kemiripan. Kita menambah cerita dan saran agar orang bisa berpikir. Nah, dalam menulis, penulis juga bisa menambahkan cerita untuk membawa orang “masuk” ke dalam kisah yang sedang ditulis. Misalnya, saya mulai Majapahit dengan cerita soal Kertanegara memotong kuping Mengzi. Dengan konteks sekarang, ini sama ketika ada orang Indonesia yang memotong kuping duta besar Amerika dan mengirimnya ke Washington. Ini pasti jadi berantem. Penulis bisa memasukkan “drama” dalam tulisannya, menggunakan visualisasi, agar cerita enak dibaca.
IL:
Ya, dari penjelasan ini saya setuju bahwa seorang penulis adalah seniman.
JS:
Saya pertama bertemu Herald saat mengerjakan Jakarta: History of Misunderstood City. Menurut saya, sebuah cerita memang harus hidup. Satu contoh adalah J.K. Rowling yang bisa membuat anak-anak seperti seolah-olah “tersihir” oleh kisahnya. Buku setebal 540 halaman bahkan bisa dibaca dalam waktu dua hari!
Dengan Majapahit, saya kira juga bisa mendorong agar orang asing mulai mengenal Indonesia. Satu contoh, orang mancanegara lebih mengenal Angkor Wat daripada Borobudur.
Saya menyebut satu buku lain yang ditulis orang asing tentang Indonesia, A Brief History of Indonesia. Buku ini sebenarnya terinspirasi ketika belajar di Amerika Serikat. Saat itu, pada hari pertama saya harus membuat ringkasan dari buku tentang sejarah Amerika Serikat yang harus dikumpulkan esoknya. Saya menyadari bahwa setiap pelajar asing harus membaca sejarah Amerika Serikat. Nah, A Brief History of Indonesia ini ditulis oleh orang Inggris yang pernah menjadi guru di EF (English First) di Surabaya, Tim Hannigan. Tim ini adalah seorang peselancar. Dia pernah naik sepeda motor bebek dari Surabaya ke Jakarta. Dia juga memiliki gelar Ph.D. untuk bidang penulisan kreatif.
Buku Tim menceritakan sejarah Indonesia dari zaman prasejarah hingga era Jokowi. Buku ini juga telah digunakan di beberapa kampus untuk mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.
HL:
Benar, Indonesia tidak begitu dikenal di luar negeri. Saya pernah mengecek ke beberapa kenalan apa yang diketahui tentang Majapahit. Mereka mengira itu nama kue! (Audiens tertawa.) Padahal, kenalan saya itu sudah tinggal selama 40 tahun di Asia.
Tapi, apa yang ingin saya sampaikan bukanlah cerita soal kue. Yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya tulisan yang membuat pikiran kita tajam. Kita bisa membahas apa saja. Tapi, ketika kita bisa menuliskan itu dan menjelaskan kepada orang lain, kita bersikap proaktif. Misalkan saja dalam hal memasak. Saya tidak bisa masak, tetapi saya bisa melihat video tutorial memasak rendang, saya harus mencobanya. Ya, mungkin istri saya akan bilang: “Kamu harus pakai bumbu ini-itu, begini-begitu.” Saya harus mencoba lima atau enam kali membuat rendang baru terasa enak.
Nah, inilah sikap proaktif. Dan, di situlah kita belajar. Kita memang harus menulis untuk bisa proaktif belajar secara mendalam. Kita harus bisa menulis kembali gagasan-gagasan yang kita baca dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Nah, itulah mengapa menulis itu mempertajam pikiran.
IL:
Dan, uniknya di Indonesia ini, kita memiliki begitu banyak cerita. Tapi, yang kurang dari kita adalah para pencerita. Padahal, saat ini kita menghadapi globalisasi dan berkompetisi dengan negara-negara tetangga yang mungkin cerita mereka tidak sebanyak yang kita miliki. Namun, mungkin mereka memiliki para pencerita yang lebih baik. Bagaimana kita berkompetisi dengan mereka?
JS:
Menurut saya, saat ini, generasi muda harus bisa menulis dengan baik menggunakan bahasa Inggris, sebagai bahasa pergaulan internasional. Anak-anak memang harus dilatih menjadi poliglot, bisa menguasai beberapa bahasa, utamanya dalam hal menulis. Namun, mereka juga tidak boleh melupakan bahasa ibunya. Bahasa Indonesia menjadi utama, namun juga wajib menguasai bahasa Inggris. Sebab, di sinilah kita bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Saya tidak tahu bagaimana nanti lima puluh tahun mendatang, namun kemampuan berbahasa Inggris menjadi sungguh penting bagi anak-anak Indonesia.
Saat ini, kalau kami membuat buku dari penulis Indonesia, saya akan meminta beberapa native speaker bahasa Inggris, mengingat saat ini belum banyak penulis Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Namun, saya rasa, kita perlu yakin dalam lima atau sepuluh tahun mendatang akan banyak generasi muda Indonesia yang fasih menguasai bahasa Inggris.
Memang, di tahap awal, anak-anak kita harus “dipaksa” membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Namun, mereka juga memerlukan apresiasi. Misalnya, di sekolah anak sudah menceritakan refleksinya tetapi tidak ada respon dari gurunya, nanti anak tidak akan merasa bangga. Seperti yang diceritakan oleh Herald tadi, anak perlu diapresiasi.
Untuk para orang tua, dan calon orang tua, kita perlu mengapresiasi dan melatih anak untuk berlama-lama membaca dan menulis. Saat ini, sekolah sudah terbiasa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Akan baik jika orang tua hadir saat anak mempresentasikan hasil pembelajarnya di sekolah. Dengan demikian, anak akan merasa terhibur dan bangga pada proses belajar yang dijalaninya.