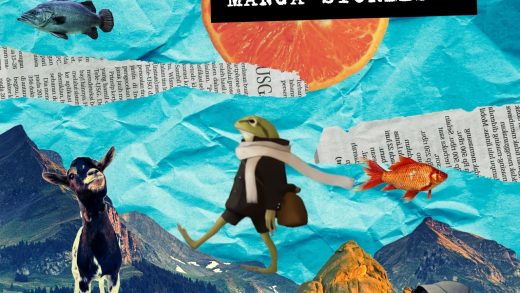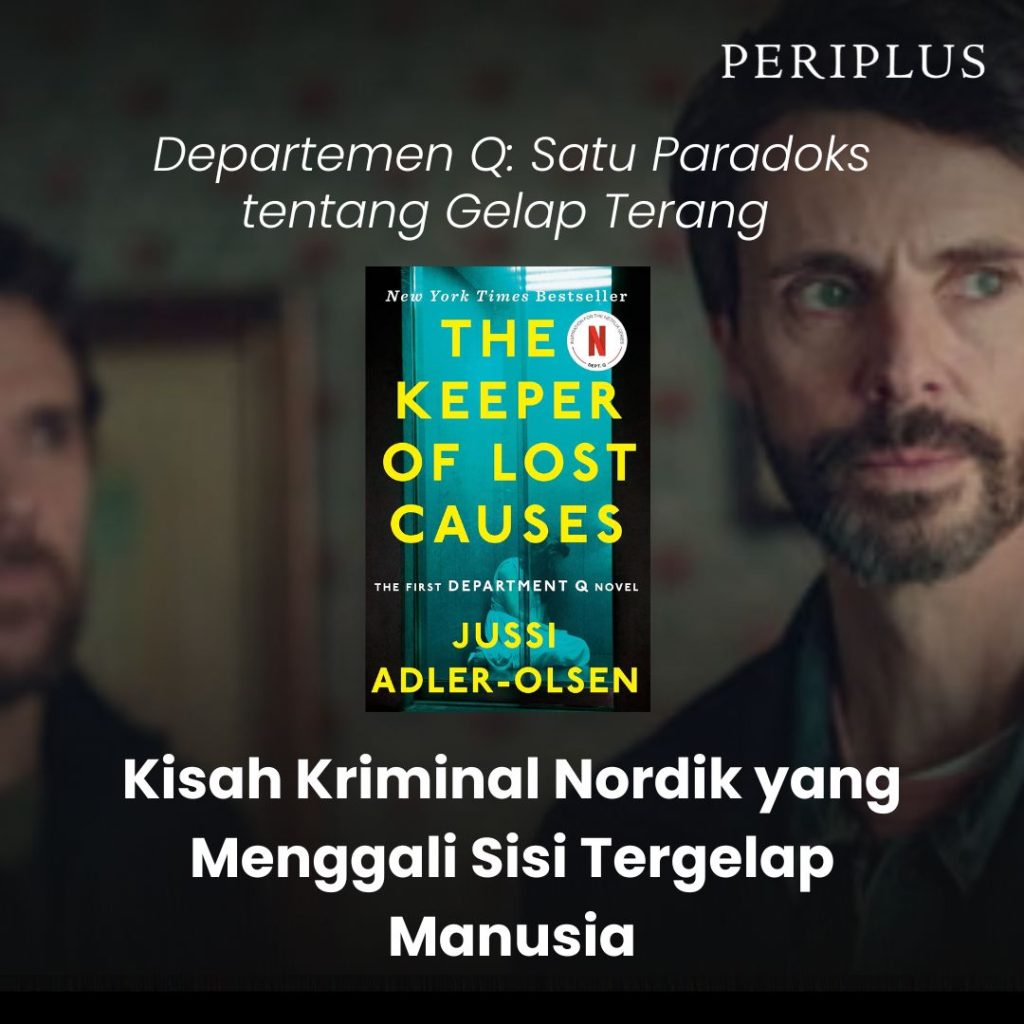
Daya pikat penceritaan terletak pada keterhubungan dua kehidupan. Pertama, kehidupan tokoh di semesta cerita dan, kedua, kehidupan si pembaca cerita. Semakin kuat, rapat, dan solid jalinan di antara keduanya, semakin cerita memiliki daya pikat yang tidak dapat dielakkan. Uniknya, manusia dan cerita terhubung oleh satu kata yang tidak dapat disanggah: waktu. Waktu memang menjadi unsur paling krusial dalam penceritaan. Tanpa waktu, cerita tidak akan berjalan. Tanpa waktu, karakter tidak akan berkembang atau menyusut. Tanpa waktu, pembaca akan memasuki limbo; ruang tepian antara yang ada dan tiada. Khusus untuk kisah-kisah detektif, elemen waktu ini juga menjadi krusial. Apa yang sedang dikerjakan penjahat, bagaimana kejahatan terjadi, motif apa yang tersembunyi di benak orang jahat, dan apa-apa saja yang harus dikuak oleh para detektif untuk memecahkan kasus—semuanya itu berada dalam alur waktu.
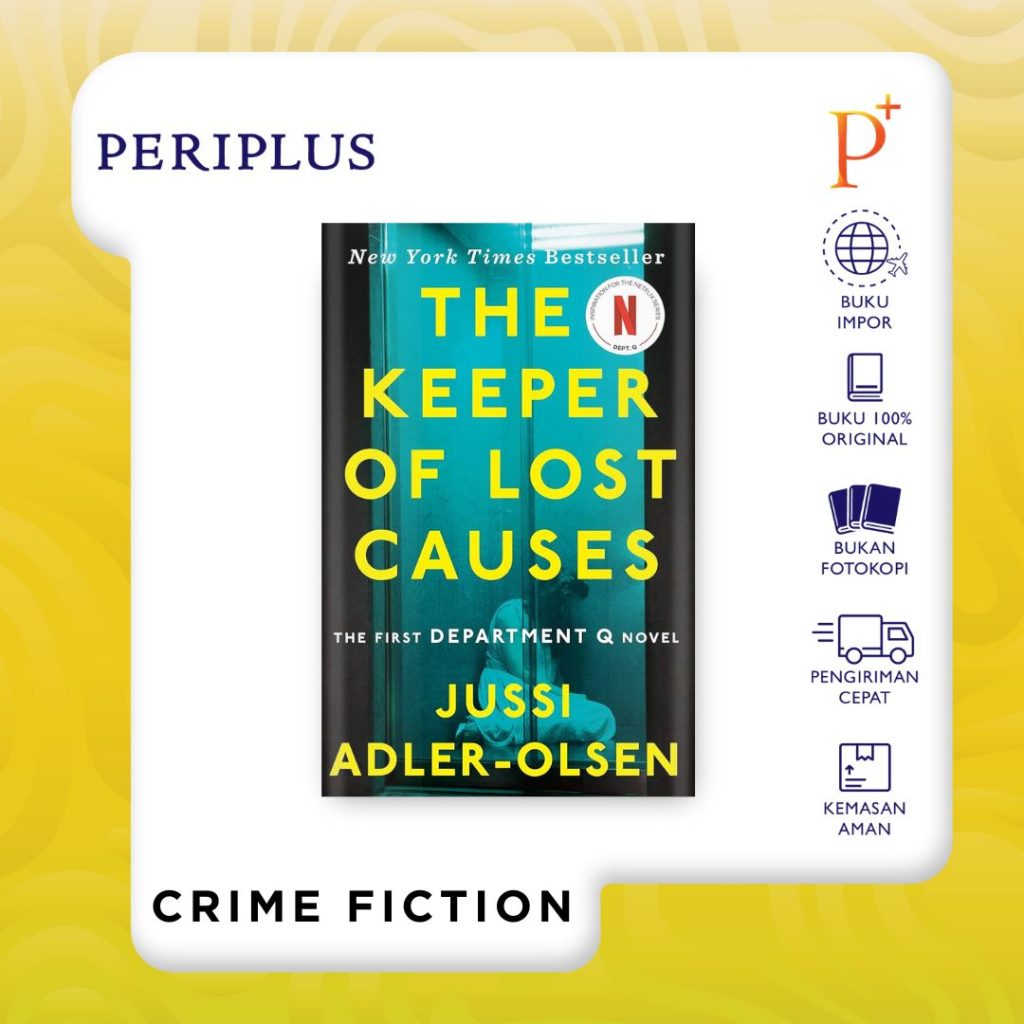
ISBN-13: 9780452297906
Carl Mørk yang terbuang
Syahdan, tersebutlah Carl Mørk, seorang detektif senior dari kepolisian Kopenhagen di Denmark, mengalami musibah yang mengubah alur kehidupannya. Saat melakukan penyelidikan atas sebuah kasus pembunuhan, ia tertembak. Satu polisi muda bahkan tewas dan rekannya, sesama detektif, mengalami kelumpuhan. Peluru si penjahat menembus leher Carl. Dan, sebagaimana para jagoan lain di dalam cerita, Carl luput dari kematian. Setelah kembali bertugas, ia “dibuang” ke Departemen Q, yang ada di bawah tanah, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah “masuk peti es”. Parahnya hal ini berpengaruh pada kondisi mentalnya. Carl menjelma menjadi pribadi yang didera rasa bersalah dan penyesalan atas kematian dan kelumpuhan dua rekannya. Selain itu, rasa sinis terhadap institusi tempatnya bekerja menebal, mengikis rasa percayanya pada sistem. Sayangnya, kondisi ini diperburuk oleh konflik internal kepolisian yang seolah tak ada ujung dan pernikahannya yang carut-marut—setelah berpisah dari istrinya, Carl tinggal bersama anak sambungnya, seorang remaja pemberontak yang merindukan sosok ayah.
Di balik segala luka dan kerapuhan manusiawinya, Carl masuk ke babak baru kehidupannya. Dan, tepat di sinilah, Jussi Adler-Olsen membuka babak baru bagi salah satu fiksi kriminal paling memikat dari gerbong Nordic Noir yang juga telah dihuni oleh para penulis kenamaan seperti Jo Nesbø, Henning Mankell, Stieg Larsson, Camilla Läckberg, atau Arnaldur Indriðason. Kisah pembuka serial ini sendiri hadir dalam dua versi, Mercy untuk Inggris dan The Keeper of Lost Causes untuk Amerika Serikat. Di dalam novel pembuka ini, setidak-tidaknya ada tiga hal penting yang perlu diberi perhatian. Pertama, tentu saja, perkenalan karakter, terutama pada sosok Carl Mørck. Kedua, bagaimana Detektif Mørck membangun tim bersama dengan Assad dan Rose. Yang terakhir adalah bagaimana departemen baru ini memecahkan kasus hilangnya seorang politisi muda yang menjanjikan, Merete Lynggaard.
Carl Mørck adalah sosok yang emosional, sinis, penuh masalah, sarkastik, dan dipenuhi pergulatan batin—meskipun memiliki kecerdasan serta insting jempolan sebagai detektif untuk kasus-kasus pembunuhan. Uniknya, di Departemen Q, Mørck kemudian dibantu oleh Hafez el-Assad yang memiliki kepribadian bertolak belakang sama sekali dengan Mørck. Assad adalah pribadi yang sopan, cerdas, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, meskipun misterius. Assad di awal cerita menyembunyikan latar belakangnya. Ia hanya dikenal sebagai imigran dari Timur Tengah. Awalnya, Assad hanya ditugaskan sebagai “pembantu kebersihan” di Departemen Q, namun kemudian menunjukkan kemampuan investigatif di atas rata-rata. Assad yang memiliki karakter yang lebih humoris, sehingga menjadi penyeimbang bagi Mørck. Selain itu, Assad juga memiliki sisi gelap di masa lalunya terkait perang dan penyiksaan. Di lain sisi, ada pula sosok Rose Knudsen, perempuan penuh semangat, yang kadang temperamental, blak-blakan, dan tegas. Kehadiran Rose dalam tim ini sering kali menjadi “perekat” untuk Carl dan Assad. Rose sendiri juga menyimpan sisi gelap akibat kekerasan yang dialaminya semasa masih kecil.
Sembari menjalani “masa pembuangan”, Carl Mørck tertarik pada kasus hilangnya seorang perempuan muda yang juga seorang politisi yang tengah berada di puncak kariernya, Merete Lynggaard. Kasus ini membawa Mørck dan departemen yang dipimpinnya kembali ke masa 2002. Lynggaard dinyatakan hilang selama lima tahun. Orang-orang pun telah menganggapnya meninggal. Namun demikian, Carl dan kawan-kawan menemukan beberapa kejanggalan yang menuntun pada kemungkinan bahwa Merete masih hidup. Jussi Adler-Olsen merangkai kisah yang menegangkan dan penuh kejutan. Seri pertama ini membuat pembacanya masuk dalam investigasi kasus yang sistematis, namun juga kisah yang seru. Belum lagi, kita perlu memberi ruang pada hubungan yang terjalin dari Carl, Assad, dan Rose—juga latar belakang masing-masing yang sungguh manusiawi.
Eksplorasi Jussi Adler-Olsen
Jussi Adler-Olsen memiliki kepiawaian untuk berkisah dan membuat jalinan antara dua lapisan cerita. Pada satu lapisan, kepada kita disuguhkan investigasi yang dilakukan oleh Carl dan timnya. Satu lapis yang lain menyuguhkan perkara-perkara yang dialami oleh Merete Lynggaard. Berkat kepiawaian penceritaan yang demikian, dalam benak pembaca tentu akan menimbang-nimbang beberapa pertanyaan yang mengambang di benak. Titik-titik buta apa saja yang luput dari perhatian para penyidik sebelum Carl? Apa saja rahasia yang disembunyikan dari kasus yang dialami Merete Lynggaard? Apakah benar bahwa Merete tewas setelah hilang dari feri yang ditumpanginya, seperti keyakinan banyak orang? Dan, dari rentetan pertanyaan inilah kasus penyelidikan Departemen Q benar-benar bermula.
Kasus Merete Lynggaard dalam seri pertama Departemen Q menyimpan aspek penyelamatan yang coba ditawarkan oleh Adler-Olsen. Carl memang berhasil menemukan Merete hidup-hidup. Namun demikian, terpecahkannya kasus Merete juga membawa penebusan bagi kehidupan “baru” Carl Mørck. Hubungan dengan dasar imbal-balik seperti inilah yang justru membuat sosok Mørck sebagai jagoan yang tetap manusiawi. Sebab, selain berhadapan dengan urusan “pembuangan”, Carl juga menghadapi persoalan yang jauh lebih besar dari dirinya: perkara otoritas dan seluk-beluk institusi. Pada kisah-kisah selanjutnya, Departemen Q akan berhadapan dengan orang-orang yang memang memiliki disfungsi dalam hal moral dan etika. Namun demikian, tidak jarang bahwa orang-orang semacam itu juga dilindungi oleh kekuasaan, berbalut harta, pun oleh ribetnya birokrasi. Di tengah impitan pengalaman gagalnya sebagai manusia di beberapa aspek, dalam kehidupan Carl Mørk masih terdapat celah untuk merayakan sesuatu melalui kasus-kasus yang dipecahkannya.
Departemen Q memang secara eksplisit masuk pada eksplorasi sisi gelap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah sistem sosial. Tema-tema seperti pengabaian, trauma, maupun kegagalan sistem masyarakat memberi perlindungan pada kerentanan manusia coba diangkat oleh serial ini. Hal ini bukan tanpa dasar dan latar belakang. Jussi Adler-Olsen sendiri dibesarkan dalam pengaruh ayahnya, yang seorang dokter jiwa. Sejak kecil, Jussi sudah sering melihat “kegilaan” dan sisi gelap manusia. Dalam sebuah kesempatan, Jussi bahkan menceritakan bagaimana dirinya “berteman” dengan seorang pembunuh yang dirawat di rumah sakit jiwa. Orang itu adalah pembunuh istrinya sendiri. Dan, akibat perbuatannya, pada akhirnya orang itu menderita gangguan jiwa. Jussi mengakui bahwa pengalaman inilah yang memberi pelajaran tentang apa makna kebaikan dan kejahatan. Secara ringkas, Jussi Adler-Olsen menganugerahkan kepada kita Carl Mørck, seorang detektif yang juga manusia biasa penuh kerentanan dan keretakan batin. Ia tidak hanya menyelidiki persoalan kejahatan, namun juga melakukan penyelidikan pada dirinya sendiri, sebagai manusia.
Tentang suara yang lesap
Saat ditanya siapa penulis yang membawa pengaruh besar pada aspek kepenulisannya, Jussi dengan gampang menjawab bahwa John Steinbeck adalah penulis yang diidolakannya. Alasannya sederhana, Steinbeck membawa suara-suara yang lesap (the missing voices) sehingga menjadi terdengar oleh sebanyak mungkin orang. Dan, menurut Adler-Olsen, dalam sebuah karya sastra, salah satu suara yang hilang tidak lain adalah suara pembaca itu sendiri. Di dalam dunia musik, misalnya, suara yang lesap adalah suara pendengar.
Penjelasan yang ditawarkan Adler-Olsen sederhana. Seorang musisi atau penulis musik, bisa membuat musik dengan teori secanggih mungkin. Namun, seorang musisi yang baik akan bisa memunculkan suara yang hilang dari pendengarnya. Dan, itu terjadi saat pendengar bisa mendendangkan lagu yang didengarnya, atau setidak-tidaknya, menyanyikan lagu itu dalam hati. Bisa jadi, di sinilah letak kekuatan Department Q: ia bukan hanya membuat kita penasaran tentang siapa pelaku kejahatan, tetapi juga mengingatkan kita akan suara-suara yang nyaris hilang dalam diri kita sendiri—suara penyesalan, belas kasih, dan keberanian untuk memaafkan, terutama memberi maaf kepada diri sendiri.
***
Pada akhirnya, Departemen Q bukan hanya ruang bawah tanah di markas kepolisian Kopenhagen. Ia adalah metafora bagi ruang batin manusia yang terlampau lama disembunyikan di dalam arsip kenangan, rasa bersalah, dan kehilangan. Di sanalah Jussi Adler-Olsen menyalakan lentera kecil—melalui Carl, Assad, dan Rose—untuk mencari kembali hal-hal yang dianggap telah hilang: keadilan, kasih, dan pengampunan.
Dari perkara kejahatan yang hendak dibongkarnya, Departemen Q—yang berkantor di ruang bawah tanah yang pengap, lembap, dan sunyi—mencoba memperdengarkan suara-suara lesap para korban kejahatan. Melalui rangkaian kisah Departemen Q, Jussi Adler-Olsen ingin menegaskan sebuah paradoks abadi dalam hidup. Yakni, justru di tengah kegelapan yang begitu pekat, secercah cahaya justru menemukan kepenuhan maknanya. Justru melalui Departemen Q yang tersingkir, dengan pribadi-pribadi yang sempat tinggal di kegelapan, terang keadilan bagi suara-suara lesap justru hendak dipancarkan.
Jika Bibliobesties hendak membaca ulasan Perimin lainnya, temukan di sini!