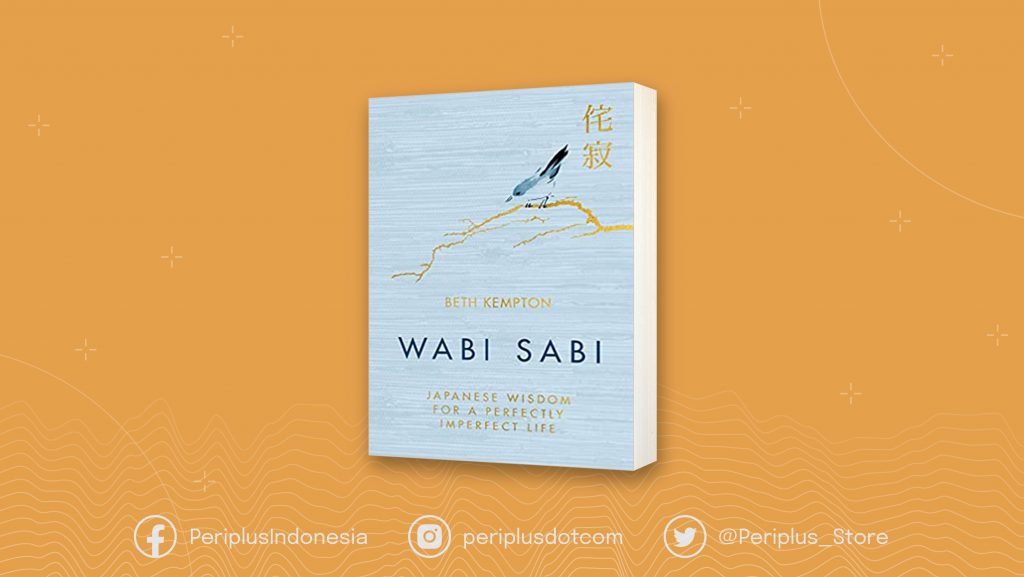
Hampir dua dasarwarsa yang lalu, Jepang dan Korea menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Saat itulah terjadilah “reuni” antara Jerman, Italia, dan Jepang sebagai blok sentral dengan blok sekutu pasca Perang Dunia II. Pasukan sebelas pas dari sekutu antara lain adalah Amerika, Perancis, dan Inggris. Bukan, bukan untuk beradu mesin perang, namun mereka beradu mesin gol. Perang di atas tidak menimbulkan kepedihan maupun dukacita yang tak terobati. Justru, seluruh jalan-jalan di setiap kota dipenuhi gegap-gempita merayakan kebahagiaan yang sama. Yokohama Jepang pun menorehkan sejarah sebagai lapangan tanding kelas pemuncak kompetisi empat tahunan ke-17 ini. Kala itu, keindahan tarian samba tim Brasil mampu mengungguli permainan kolektif berpadu staying power ala tim panser Jerman. Sayang, Jepang harus menerima diri dan kenyataan lantaran gugur di babak 16 besar. Wabi sabi!
Ini adalah kali pertama gelaran sepak bola terakbar sejagad dipentaskan di tanah Asia, tepatnya batas timur Benua Kuning. Tidak sedikit dari orang sedunia mengagumi segala hal tentang budaya Jepang. Arsitektur, makanan, pakaian, seni tari serta bonsai adalah beberapa hasil kebudayaan mereka yang menarik di mata orang dari negeri lain. Selain budaya tersebut, etos kerja dan kemampuan mereka dalam mengembangkan teknologi membuat banyak orang mengacungkan keempat jempol. Lebih dari itu, orang Jepang pun diapresiasi karena masih merawat dan menghidupi kebudayaannya yang menarik banyak wisatawan berkunjung ke Negeri Matahari Terbit ini.
Lalu, apakah raison d’etre dari anggapan bahwa Jepang begitu Istimewa? Dilihat dari budayanya, kebijaksanaan adalah buah yang paling riil nan reflektif untuk banyak orang. Salah satu kebijaksanaan Jepang yang patut untuk direnungkan adalah wabi sabi.
Judul: Wabi Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life]
Penulis: Beth Kempton
ISBN: 9780062905154
Tahun: 2018
Halaman: 256 hlm.
Dari zen ke wabi sabi
Sebenarnya, apa saja yang membuat orang Jepang begitu menghargai kebudayaannya? Untuk menguraikan teka-teki ini secara presisi, kita harus kembali menengok masa lalu Jepang. terutama setelah masuknya Agama Buddha.
Pada waktu itu, Agama dimulai oleh Siddharta Gautama di India terbagi menjadi dua cabang besar yaitu Mahayana & Hinayana. Agama Buddha Mahayana akhirnya masuk ke Jepang dibawa oleh para Biksu dan penganutnya. Migrasi ini masuk bersamaan dengan diibangunnya hubungan diplomatik dan dagang antara Jepang dengan China maupun Korea. Dalam proses inkulturasi, ajaran agama tersebut berkembang bersama, saling melengkapi, dan menata kembali kebudayaan Jepang. Alhasil, proses elaborasi ini bertumbuh subur hingga menjadi sentrum kebudayaan dunia. Tidak berhenti di sana, banyak kalangan juga masih setia untuk mengejawantahkan bahwa produk masa lalu itu selalu aktual.
Melalui kehadiran agama Buddha ini pulalah, zen memiliki dampak yang besar dalam khazanah budaya Jepang. Bisa dikatakan, zen menjadi saka guru dalam membangun identitas budaya. zen identik dengan meditasi dan refleksi atas diri, sesama, dan alam semesta. Identitas itu diwujudnyatakan dalam bentuk-bentuk kebudayaan yang konkret dan kaya namun dalam sebuah ruang yang sederhana. Transformasi tersebut masih dapat kita saksikan dan alami dalam acara minum teh, seni tanaman kerdil atau bonsai, dan ikebana alias seni merangkai bunga.
Menakar kata, menuai makna
Wabi sabi terdiri dari dua kata yang berpijak pada nilai yang indah dan berakar pada literatur, budaya, dan agama. Sebagaimana diuraikan di atas, wabi sabi adalah wujud elaborasi kebudayaan dan agama. Wabi adalah tentang menemukan keindahan dalam kesederhanaan; pun tentang kekayaan dan keluhuran nilai spiritual dalam materi duniawi. Sabi lebih menitikberatkan soal perjalanan waktu, mulai dari tumbuh kembang sampai pada akhirnya membusuk layu dari sesuatu. (p. 10)
Memaknai wabi sabi tak elok rupanya jika hanya dari etimologis semata, karena sejatinya memang lahir dari budaya dan warisan agung orang Jepang. Wabi sabi hidup secara inhern dalam tepi kesadaran dan mengakar dalam hati mereka. Wabi Sabi adalah perasaan nyata tetapi sekaligus tidak berwujud (p. 17).
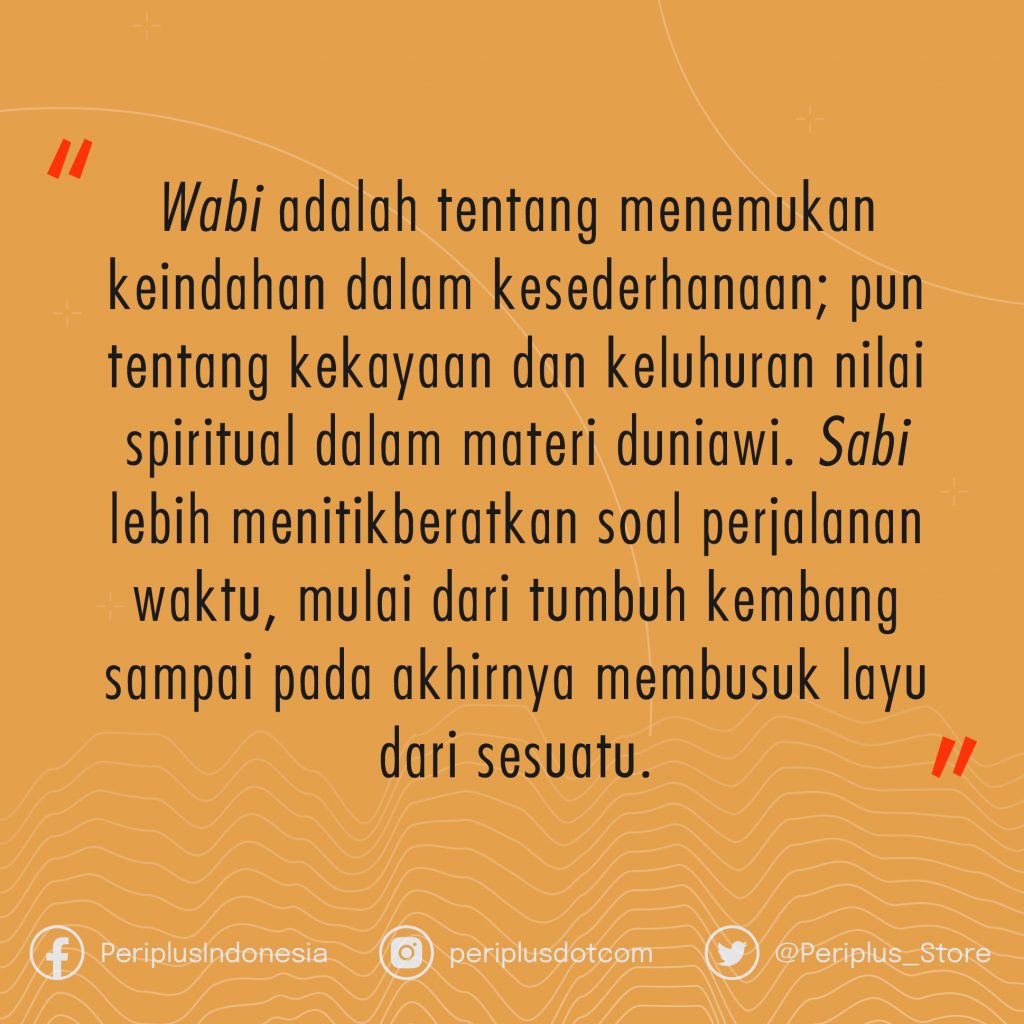
Kembali ke alam
Salah satu konsep utama wabi sabi adalah kembali ke alam, bersahabat dan bekerja sama dengan alam. Melalui pengalamannya bertahun-tahun tinggal di Jepang, penulis buku mengajak pembaca yang budiman menyelami makna wabi sabi. Salah satu pengalaman itu antara lain Refleksi Hutan. Dari kegiatan ini, para peserta diajak untuk kembali memeluk alam. Memeluk pohon, merasakan keindahan sekitar baik melalui sentuhan, pengecap, pendengaran maupun penglihatan lalu merefleksikannya secara pribadi bersama alam sekitarnya. Dalam hal yang lebih sederhana, kedekatan dengan alam diapresiasikan melalui peralatan sehari-hari dari kayu dan batu yang bisa didapat langsung dari alam.
Pengaruh wabi sabi lebih kuat dan terasa dalam arsitektur jepang dan gaya hidup mereka sehari-hari. Contoh paling jelas antara lain tentang pemanfaatan ruangan dalam rumah. Arsitektur rumah dibuat secara sederhana: banyak ruang kosong dan ditata seolah menyatu dengan alam. Desain yang menganut tata ruang tradisional dibuat menjadi ruang serba guna, baik sebagai tempat makan, tempat berkumpul keluarga maupun sebagai ruang tidur bersama. Secara sederhana, bisa dikatakan satu untuk semua atau dalam bahasa yang lebih mentereng, one stop living.
But, Wabi Sabi teachs us to enjoy the aging process and to relax into it as the most natural of thins.
(p. 180)
Selain soal bangunan “jasmaniah”, bangunan “rohaniah” menjadi ruang mewujudnyatakan semangat wabi sabi, misalnya saja perayaan tahunan. Seluruh elemen masyarakat terlibat dalam acara peryaan tahunan, tanpa terkecuali. Merayakan bersama keluarga pergi ke kuil untuk berdoa dengan mengenakan kimono untuk perempuan. Kesetiaan membalut diri dengan pakaian tradisional ini adalah menjadi cara merawat dan menghargai warisan kebudayaan leluhur.
Seperti halnya ketika kita menikmati makanan, pasti ada suatu rasa yang melekat di dalam mulut dan menjadi signature atasnya. Kita menyebutnya after taste atau rasa ikutan. Dari dunia teh, misalnya, ketika menyesap teh hijau, rasa ikutannya bisa jadi adalah manis dan aroma yang segar karena kemurnian teh itu sendiri. Dalam konteks merawat kebudayaan dan tradisi, after taste yang muncul adalah kepuasan dan mungkin susah untuk dikatakan, yang jelas sangat mengesan di persaan. Rasa ikutan yang menyeruak dari menjaga tradisi adalah terjaganya warisan budaya material dan non material. Selain itu, nilai sosial-kultural ini ternyata menjadi daya tarik bagi wisatawan dari mancanegara untuk menyambanginya.
Di saat yang sama, imbas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh terasa di Jepang, mereka tidak melupakan tradisi wabi sabi yang sudah berusia ratusan tahun.
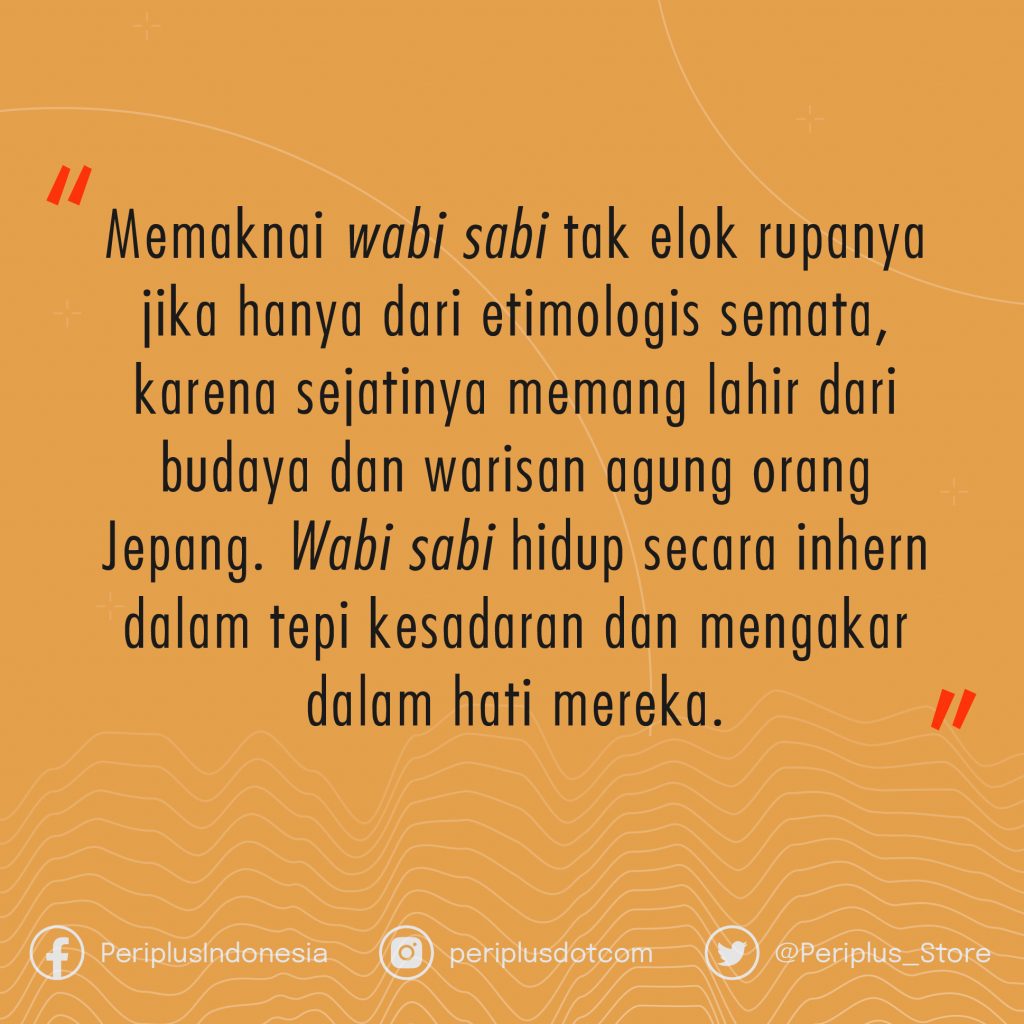
Revitalisasi semangat wabi sabi
Secara umum, buku ini bagus untuk mengenalkan filosofi dan kebiasaan masyarakat Jepang, terutama dari sudut pandang bukan orang Jepang. Beth mengungkapkan demikian, “Pandanganku tentang wabi sabi akan selalu dalam konteks diriku yang adalah orang Barat sejak kecil lalu terpengaruhi oleh ‘hubungan asmara’ selama dua puluh tahun dengan Jepang.” Ia mau menegaskan bahwa buku ini ditulisnya jauh dari kemurnian asali. Meski demikian, tidak berarti bahwa ia melenceng jauh, tetapi berusaha untuk tetap senada-selaras dengan budaya Jepang dalam usaha menemukan kecantikan mendalam dari wabi sabi. “Sebab, wabi sabi memberikan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri,” tegas Beth di halaman 25.
Pengalaman tinggal selama puluhan tahun dan usaha untuk mempelajari budaya lokal memberikan kemampuan penulis untuk menyelam lebih dalam. Tinggal dan hidup bersama masyarakat dilalui saban hari dengan penuh semangat untuk belajar. Proses ajur-ajer ini membawa penulis untuk membuka diri agar mampu merasakan kemudian mengaplikasikan nilai-nilai sosial yang didapatkan dalam hidupnya sendiri. Tinggal dan berbuah merupakan kata yang tepat untuk usaha penulis mengekspresikan “pengalaman berproses” menjadi tulisan yang sangat realistis penuh makna.
Di bilik yang lain, ada beberapa narasi kami rasa perlu dikembangkan lebih jauh dari buku ini. Memang buku ini hanyalah pengantar, tetapi alangkah lebih baik jika ditambah beberapa hal lagi. Ada tiga hal.
Pertama, apa yang perlu direvitalisasi dalam penulisan buku ini adalah sosok yang menerapkan wabi sabi sejak kecil sampai—minimal—remaja. Kami rasa, buku ini akan menjadi makin hidup bilamana memiliki bagian khusus untuk menampilkan penghidup tradisi asli Jepang. Testimonial mengenai usaha dalam menghidupi wabi sabi dari orang lokal akan memperkuat insight bagi para pembaca. Bagian ini diharapkan membahas tentang pengalaman pribadinya dan lingkungan sekitarnya dalam menerapkan filosofi ini sejak kecil. Narasi akan terasa makin kuat karena sosok yang lahir, tumbuh, dan hidup di Jepang sungguh mengalami situasi suka-duka hidup dalam lingkungan yang sungguh alami. Buku ini seharusnya tidak kurang roh.
More important, accepting imperfection doesn’t mean having to lower standards or drop out of life.
(p. 24)
Kedua, di awal tulisan penulis dengan menarik dan mengajak para pembaca mengenali dan mengaplikasikannya dengan sederhana secara pribadi. Akan tetapi, setelah itu buku ini seolah hanya membahas pengalaman pribadi penulis dan hasil refleksi penulis mengenai wabi sabi. Sayangnya, perubahan ini membuatnya berubah menjadi buku yang umum ditemukan tentang penerimaan diri atau mungkin self-help. Mungkin akan berbeda jika pengamalan wabi sabi dalam proses penerimaan diri tersebut dibahas lebih mendalam. Yang jelas, horizon pengembangan ide dan alur tulisan masih sangat bisa diluaskan lagi.
Terakhir, seperti kita ketahui bersama bahwa Beth bukanlah orang asli Jepang. Dia bukan seorang yang lahir di Jepang dan menghidupi budayanya semenjak kanak-kanak. Hal ini berimbas pada penyampaian yang mungkin kurang bisa merasakan emosi yang dialami oleh masyarakat Jepang sendiri. Misalnya saja tentang menerima kegagalan. Kaum muda Jepang memiliki tekanan untuk sukses masuk universitas dan memiliki karir yang bagus untuk mengimbangi standar hidup yang sangat tinggi. Orang Jepang juga terkenal memiliki budaya malu yang berakhir dengan banyak contoh pengunduran diri atau bahkan sampai bunuh diri karena kegagalan melaksanakan tugas. Wabi sabi seharusnya bisa menjawab persoalan sosial semacam ini, karena dia adalah budaya yang tumbuh dari dan di dalam sukma orang Jepang.




