
Apa yang saya tulis melalui artikel ini terinspirasi dari 3 film yang pernah saya tonton. Tentu, temanya seputar pendidikan dengan gaya yang out of the box. Artikel ini dibuat dalam rangka program Aku Pendidik Indonesia 2022.
1. Taare Zamen Par
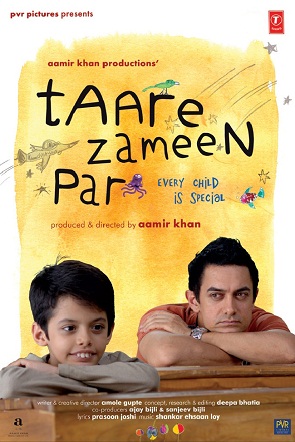
Ishaan (8 tahun) menjadi bahan olokan beberapa orang. Mulai dari kesulitan membaca (disleksia), tidak bisa menulis sampai niscaya gagal dalam semua ujian. Bagi sistem pendidikan lazim, Ishaan adalah contoh murid yang gagal. Namun tidak bagi Nikumb, seorang guru seni yang mengajarkan pentingnya imajinasi dan keberanian untuk berpikir out of the box. Dengan pendampingan yang begitu personal, semua pihak diajak oleh Nikumb untuk melihat keindahan dunia dalam kepala Ishaan. Ishaan menunjukkan bakatnya dalam dunia melukis, yang amat disayangkan kurang mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan yang lebih mengunggulkan logika deduktif atau hapalan tata bahasa. Sampai pada akhirnya, semua orang melihat Ihsaan tidak lagi sebagai olokan atau siswa yang gagal, melainkan siswa yang begitu istimewa – asalkan, sistem pendidikan mampu menghargai perbedaan di setiap diri peserta didiknya.
2. Hichki

Naina Mathur, seorang guru yang diminta untuk mendampingi kelas 9 yang berisi anak-anak bermasalah dan merundung para guru yang masuk untuk mengajar mereka. Intinya, tidak ada yang mau mengajar anak-anak ini. Keusilan demi keusilan dialami Naina selama masuk ke kelas tersebut. Hampir putus asa. Sampai akhirnya, Naina memutuskan untuk melakukan visitasi ke rumah anak-anak ini. Naina miris melihat kondisi anak-anak ini. Mereka bukanlah anak bermasalah, melainkan anak-anak yang tidak memiliki pemandu hidup. Tidak ada yang mengarahkan mereka. Naina menyadari bahwa setiap keusilan yang mereka lakukan adalah kreativitas tanpa arah. Naina mengarahkan dan membantu mereka menemukan keunggulan mereka satu persatu. Satu persatu! Sampai akhirnya, sekolah pun bangga dan berterima kasih karena kehadiran mereka.
2. Hichki
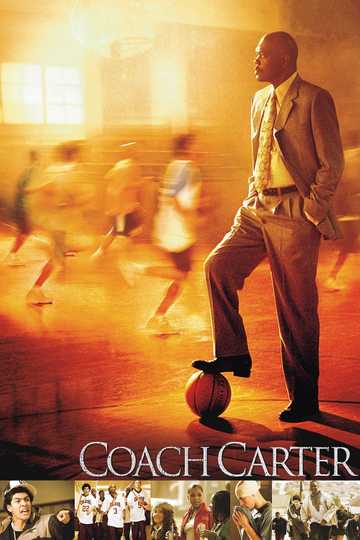
“Kamu hanyalah pelatih basket mereka. Kamu tidak perlu mengurusi mau jadi mereka nantinya.!”
Ken Carter, pelatih basket SMA Richmond, bersitegang terhadap dewan sekolah dan orangtua/wali murid yang terlanjur menjudge anak-anak dalam tim basket asuhannya. Anak-anak ini cukuplah untuk datang ke sekolah, bertanding basket, dan mengharumkan nama sekolah. Tapi, tidak bagi Carter! Sekolah tidak peduli mau jadi apa mereka nanti. Beberapa alumni akhirnya berakhir di penjara sebagai penjual narkoba, bahkan kembali ke Sang Pencipta. Carter yakin anak-anak ini lebih hebat dari yang mereka kira. Mereka bisa memiliki masa depan yang lebih cerah daripada para pendahulunya yang berakhir sebagai krimimal. Dan, benar! Carter membuktikannya.
***
Saya yang pernah beberapa tahun berdiri di depan kelas sambil pegang spidol dan pegang LKS, memiliki beberapa falsafah pendidikan. Datangnya dari mana falsafah ini? Datangnya dari kemalasan saya untuk mengurusi admin ini dan itu, termasuk menghabiskan waktu berjam-jam sampai berminggu-minggu untuk mengetik kata-kata mutiara di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sekalipun malas, toh tetap saya kerjakan sebagaimana mestinya demi tercapainya cita-cita dalam Preambule UUD 1945.
Otak Tidak Didesain Untuk Berpikir (Saja)

Falsafah utama yang saya imani adalah sebuah keyakinan bahwa otak itu memang tidak didesain untuk berpikir. (Saja). Terus menerus menekankan tindakan berpikir dan berpikir malah cenderung membuat mantan-mantan murid saya jadi enggan menyelesaikan soal, lengkap dengan jalan dan prosesnya. Daniel T. Willingham, salah seorang profesor di bidang ilmu Psikologi, mengawali tulisannya pada buku Why Don’t Students Like School? dengan gagasan unik: “The mind is not designed for thinking.” Nah loh! Lantas mengapa muncul anggapan manusia sebagai animal rationale dari Aristoteles?
Saya rasa (bukan saya pikir), yang lebih dulu dirumuskan dalam gagasan Daniel dan pertanyaan tentang kepemilikan akal budi ini adalah kesepakatan soal Apa Itu Berpikir. Daniel meletakkan definisi dari ‘berpikir’ itu dalam konteks pendidikan formal. Artinya, berpikir adalah kegiatan membandingkan, menghitung, menghapal, menyelesaikan, mencari tahu, memahami, sampai menganalisa. Mudahnya, kita bisa merujuk ke taksonomi HOTS, MOTS, dan LOTS miliki Benjamin S. Bloom. Kegiatan ‘berpikir’ seperti ini yang menjadi jawaban mengapa Students Don’t Like School. Padahal, Daniel berujar, “Sebagian guru yang kutemui memilih menjadi guru karena mereka mencintai sekolah sama halnya mereka mencintai anak-anak. Mereka ingin menolong para peserta didik untuk merasakan asyiknya belajar.”
Dari apa yang disampaikan Daniel, mulai nampak 2 tindakan yang perlu kita letakkan pada tempat yang berbeda: Berpikir dan Belajar. Sepintas, orang-orangtua dari lintas jaman menyamaratakan konsep sekolah dengan belajar, dengan berpikir. Sekolah itu ya belajar. Belajar itu ya berpikir. Sudah! Di sinilah, kecintaan, asyiknya, passionnya para guru tidak bertemu dengan para peserta didik. Kalau meminjam istilah StartUp kekinian, tidak terjadi Product-Market Fit dalam Excitement Learning Journey. Learning Journey tetap berlangsung, tapi tanpa ‘exicetement’. Beda.
Product-Market Fit ini membutuhkan setidaknya tiga variabel utama. Satu, Desirability untuk menjawab, ‘Apakah yang peserta didik harapkan?’. Dua, Feasibility untuk menjawab, ‘Apa sebagai guru, aku mampu memenuhi harapan mereka?’. Dan, Viability untuk menjawab, ‘Sebegitu perlu kah? Pentingkah?’. Irisan ketiga variabel ini disebut The Most Valuable Learning Experience. Kalau meminjam kata-kata Mark Anderson, “… produk (layanan) yang mampu memenuhi kebutuhan pasar akan menciptakan pengalaman yang baik di antara keduanya.” Kita sepakati bahwa ‘yang baik’ di sini adalah soal ‘exicetement’. Ini yang hendak digarisbawahi oleh Daniel.
Kembali ke soal peran otak dalam sangkut pautnya dengan proses berpikir (yang seringkali disamakan dengan belajar; dan sekolah). Peran utama dari otak adalah merekam. Ini yang penting dipahami sejak awal. Otak merekam informasi yang didapat melalui kelima indera. Otak sendiri memang bisa ‘digunakan’ untuk berpikir. Namun, “… thinking is not the one it does best,” ungkap Daniel. Berpikir itu lama, penuh upaya, dan malah tidak pasti-pasti banget. Bayangkan Anda sedang mengendari motor sepulang mengajar. Anda harus menghitung seberapa kecepatan yang dibutuhkan agar Anda bisa tiba di rumah sesuai dengan waktu yang Anda tetapkan setelah menempuh jarak sekian kilometer. Anda harus menghitung berapa meter dimensi yang dibutuhkan oleh Anda dan motor Anda untuk menyalip di antar 2 mobil yang sedang berjalan paralel. Anda pun menganalisa mengapa Anda kesulitan menyalip angkot dari sisi kanan karena kendaran yang berlawanan dengan Anda berjalan terlalu mepet dengan marka jalan. Hitung ini, bandingkan ini, analisa itu, temukan ide ini, ambil keputusan demikian, sampai menggerakan tangan dengan tenaga sekian joule. Begitu sampai rumah, jika Anda lakukan ini setiap hari, saya berdoa agar Anda hidup bahagia.
Dari ingatan-ingatan yang terekam di dalamnya, otak (syaraf-syaraf) memerintah tubuh untuk berbuat ini dan itu berdasarkan pilihan yang diambil. Tak heran jika kerap dikatakan bahwa hidup manusia itu hanya melalui dari satu pilihan ke pilihan lain. Dalam praktiknya, berkegiatan berdasarkan manual atau panduan itu jauh lebih efektif dan efisien. Ini soal waktu, soal energi, dan soal … niat! Pun, tidak bisa dipungkiri ada beberapa hobi yang mengarah pada kegiatan ‘problem solving’, seperti bermain WORDLLE, TTS, SUDOKU, dll. Ada juga yang menikmati ide-ide segar dari TedTalk atau Podcast. Usut punya usut, ini kesenangan di balik kegiatan ‘berpikir’ ini berbanding lurus dengan ‘sejauh mana informasi’ tersimpan di memori. Semakin banyak memori tersimpan, dimungkinkan tingkat kesenangan dalam tantangan ini pun dirasakan.
Dalam kegiatan sekolah, kerap kali ada tantangan soal kegiatan berpikir atau menyelesaikan tugas. Entah soal malas, entah karena tidak peduli, atau juga karena tidak punya sarana dan prasarana untuk menyelesaikan tugas. Alat tulis dipinjam tanpa dikembalikan, misalnya. Sederhananya, jika kita menjumpai seorang peserta didik yang agak enggan menyelesaikan tugasnya dengan penuh semangat dan magis, bisa jadi bukan karena kemalasan atau ketidakpedulian. Bisa jadi, dia kehilangan informasi atau tidak ada ingatan yang terekam di dalam otaknya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugasnya.
Sebagai pendidik, pernah sesekali saya masuk ke dalam kelas dan bilang, “Saya mau ada rapat. Buka halaman sekian. Jawab pertanyaannya. Kalau bingung, coba lihat halaman sebelumnya. Semua jawaban ada di sana kok. Tinggal nyalin. Open Book!” Hasilnya, anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu dengan jawaban yang SAMA PERSIS semuanya. Di dalam benak saya, “Saya tidak suka ini, tapi mungkin mereka suka cara mengerjakan tugas seperti ini.” Desirability saya tidak berisisan dengan Viability dan Feasibilty peserta didik. Tugas terkumpul, tapi kesannya malah contek-contekan. “Tapi, mereka menikmati kan? Kelas kosong, guru tidak ada, tugas gampang, mereka bisa ngerjain sambil ngobrol.”
Dari sini, saya menyadari bahwa sekalipun otak tidak didesain untuk berpikir (saja), tapi otak didesain untuk membantu seseorang bisa meracik beragam informasi yang diterima untuk mengemukakan apa yang diharapkan (Desirabilty). Masuklah saya ke falsafah kedua, soal Self-Educated.



