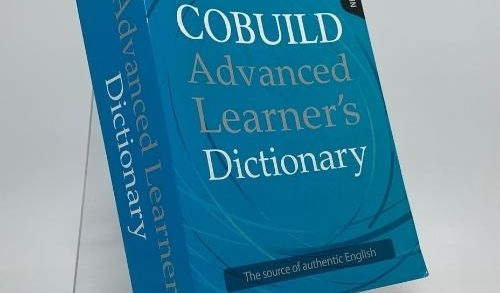Untuk tidak sedikit orang, Agustus adalah bulan yang spesial. Sejarah bahkan mencatat banyak hal luar biasa terjadi pada bulan Agustus. Pada Agustus 1774, kimiawan Inggris, John Priestley berhasil menemukan gas yang bernama Oksigen. Christophorus Colombus mengawali penjelajahan samudra menuju kepulauan Hindia pada Agustus 1492. Karya agung Lewis Carroll, Alice’s Adventure in Wonderland diterbitkan pada 1865. Adolf Hitler mendeklarasikan diri sebagai Führer pada awal Agustus 1934. Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada Sekutu pada pertengahan Agustus 1945 yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Stan Lee dan Steve Ditko pertama kali menghadirkan Spider-Man sebagai jagoan baru Marvel Comics pada Agustus 1962. Agustus 1990 juga tercatat sebagai waktu pembenihan World Wide Web. Ternyata, bulan kedelapan dalam kalender Gregorian ini bertabur peristiwa yang cukup dashyat!
Mungkin, Bibliobesties juga punya catatan-catatan personal yang terjadi pada bulan Agustus. Ulang tahun pasangan, mungkin. Atau, Agustus adalah bulan saat Bibliobesties mengalami patah hati. Ouch! Maafkan kami, kalau lukanya belum mengering. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas senormal mungkin, meskipun sakit gigi lebih baik daripada sakit hati, kata seorang biduan!
Agustus selalu istimewa!
Meskipun begitu, untuk orang Indonesia, Agustus selalu spesial. Setidak-tidaknya, dalam kalender Indonesia akan selalu ada “tanggal merah” di tengah bulan. Gagasan dasarnya tentu saja jelas: 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan ini tentu saja merujuk pada pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Sukarno pada Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang sebelumnya adalah milik Mr. Jhr. P.R. Feith, seorang advokat muda berkebangsaan Belanda. Pada gilirannya, sang pemilik rumah menjual rumahnya pada Pemerintah Republik yang baru lahir seharga f.250.000.
Puluhan tahun berselang, 17 Agustus tidak jarang dimaknai sebatas besaran ekonomis, baik dalam rupa nominal rupiah atau besaran potongan harga produk, pesta pora, saat berbelanja, dan hal-hal banal lain yang dihasilkan oleh kapitalisme dan para penyokongnya—kami sadar bahwa memanfaatkannya pula, demi kemaslahatan para pecinta buku dan bacaan bermutu! Padahal, jika kita hendak merawat ingatan, 17 Agustus adalah saat yang sakral sebagai sebuah bangsa.
Pada 17 Agustus, kita sebetulnya merawat harapan sekaligus menakar ancaman. Seorang rohaniwan sekaligus pemikir, Nicolaus Driyarkara, di awal masa bulan madu mencecap kemerdekaan pernah berkata bahwa “Negara yang sudah merdeka harus mengisi kemerdekaannya.” (A. Sudiardja, 2006:101) Driyarkara membayangkan kemerdekaan—baik dalam arti sebagai bangsa maupun pribadi—adalah layaknya sebuah “wadah” yang perlu diisi. Diisi dengan apa? Driyarkara tidak langsung menyajikan jawaban. Dia malahan mengingatkan bahwa “wadah” kemerdekaan itu pada awalnya diisi oleh ikatan-ikatan yang membelenggu.
Justru, di sinilah pokoknya, menjadi merdeka adalah momentum untuk melepas ikatan-ikatan yang membelenggu. Menjadi merdeka, menurut Driyarkara, adalah tentang memberikan diri, mencurahkan diri pada hal-hal atau orang-orang lain yang membuat dirinya tidak terbelenggu. Dan, ini semua layak untuk didasarkan pada satu kata sakti: cinta! Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang paling misterius, suatu kali pernah diinterogasi. Kepadanya diajukan sebuah pertanyaan, apakah ia seorang Bolshevik—fraksi dalam Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (RSDLP) yang menganut ideologi Marxisme dan ingin mendirikan negara sosialis Rusia. Tan Malaka menjawab demikian, “Aku bukanlah seorang Bolshevik. Seandainya rasa cinta seseorang pada negaranya menunjukkan kencenderungan kepada Bolshevisme, maka sebutlah aku sebagai seorang Bolshevik.” (Tim Harper, 2020:620)
Patriotisme toh pada galibnya sebentuk ungkapan kecintaan pada tanah air. Kutipan perkataan Tan Malaka di atas adalah pernyataan betapa kecintaan pada tanah air dan nusa bangsa berada di atas segalanya, melebihi beraga -isme yang kadang mengaburkan rasa cinta itu sendiri. Para pejuang dan pahlawan sudah tuntas memberikan diri, pikiran, dan nyawanya demi merajut kemerdekaan Indonesia yang memuncak pada 17 Agustus 1945. Agustus selalu istimewa untuk kita, karena inilah saat untuk mengenang, merayakan, dan mengirim doa bagi kelestarian negeri kita.
Merdeka butuh perjuangan, Bung dan Nona!
Menulis tentang kemerdekaan, tentu tidak bisa menafikan perjuangan. Maka, jika sekarang ini kita tidak menghadapi penjajahan fisik, lalu ikatan dan belenggu apa saja yang menghalangi kemerdekaan kita? Sebab, faktanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah lewat lebih dari tiga perempat abad yang lalu. Namun, wahai Bung dan Nona, apakah kita sudah benar-benar merdeka?
Sebelum sampai pada jawaban pertanyaan ini, rasanya perlu kita sadari bahwa kemerdekaan adalah garis finis. Sementara itu, untuk mencapai garis finis, kita perlu berlari. Ya, boleh lah naik ojol jika punya uang dan tidak mau capai. Tapi, yang pasti adalah untuk mencapai garis finis, kita harus berjuang.
Iya, sesederhana membuat mi instan tidak bisa dilakukan hanya dengan rebahan dan menjentikkan jari. Sepasti-pastinya, kita harus beranjak dari kasur, mengambil air dalam panci, memanaskan dan mendidihkan air, menyeduh mi instan, mengambil tempat untuk mencampurkan mi instan yang telah matang dengan bumbu dan bahan pelengkap lain. Mi instan yang katanya instan saja tidak se-instan itu pun! Ada rentetan proses yang harus dilalui. Yakinlah, seandainya kita belum bisa berjuang untuk dia yang senyumnya merasuk ke sanubari dan gelak tawanya membuat kita mencicipi surga, berjuanglah untuk diri kita sendiri dulu sajalah.
Masalahnya, bagaimana kita harus berjuang demi meraih “kemerdekaan” dari belenggu apa pun? Apakah berjuang itu identik dengan kerja keras bagai bagal yang melelahkan? Atau, kita bisa juga berjuang dengan “kerja cerdas”—dengan usaha seminimal mungkin meraih hasil semaksimal mungkin? Richard Koch mencoba memberikan jawaban untuk mencapai efektivitas alias “kerja cerdas” dalam The 80/20 Principle (2022). Gagasan dasar yang dipakai Koch memang bersumber pada aturan Pareto. Intinya, 20 persen waktu yang kita gunakan memberikan 80 persen hasil yang berdaya guna. (Koch, 2022: 395) Prinsip ini, kata Koch, akan membuat perjuangan kita menjadi jauh lebih efektif dan bahagia. Tapi, tetap saja, hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan “rebahan” dan semata-mata menggantungkan diri pada keberuntungan.
Toh, kita semua tahu, John Wick bahkan merajah punggungnya dengan kebijakan Romawi kuno: Fortis fortuna adiuvat—Dewi keberuntungan hanya akan menaungi para pejuang!
Medan laga kiwari, belajar bareng Baskara Putra
Merefleksikan perjuangan untuk meraih kemerdekaan masa kiwari, rasanya akan lebih adil ketika melongok pada keresahan yang dialami oleh generasi muda. Belum lama berselang, dalam kanal Endgame kita dapat merasakan dialog yang berisi keresahan antara dua generasi. Adalah Gita Wirjawan, sang pemilik kanal, yang mewakili generasi X awal dan Baskara Putra alias Hindia, sang tamu, yang mewakili generasi Millennials tengah.
Diskusi dalam kanal tersebut menjadi sangat menarik pada sepertiga bagian awal, ketika keduanya membicarakan soal kesehatan mental. Di mata Baskara, isu-isu kesehatan mental tidak lepas dari isu yang dihadapi generasi roti lapis (sandwich generation). Generasi Millennials saat ini juga lazim disebut generasi roti lapis karena harus memenuhi kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus: generasi orang tuanya, generasinya sendiri, dan generasi anaknya. Secara umum, keresahan utama dari generasi muda zaman sekarang adalah apakah bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dari hari ke hari.
Baskara bahkan menyatakan secara tegas kelamnya medan laga yang dihadapi oleh generasi muda kiwari. Menurutnya, “generasi muda yang ada di atas dan bawah seolah-olah berada di dalam biduk yang tengah karam.” Inilah generasi yang menurut Baskara benar-benar sudah tak memiliki daya lagi dikepung keadaan masa kini: permasalahan politik, krisis iklim—belum lama ini bahkan Chef Renatta Moeloek bahkan mengepos soal buruknya kualitas udara di Jakarta di media sosialnya—inflasi ekonomi, hingga impitan teknologi dalam rupa kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI—menurut Mo Gawdat dicandra sebagai entitas cerdas nan menyeramkan). Visi kelam yang diungkapkan Baskara menjadi makin pekat saat Gita Wirjawan menegaskan pandangan apakah berarti Baskara tidak melihat “cahaya terang” menyongsong 2045—saat Indonesia nanti memasuki umur kemerdekaan yang ke-100 tahun.
Kelesuan yang dialami anak muda zaman sekarang akibat impitan kondisi politik, krisis iklim, inflasi ekonomi, dan kegagapan teknologis ini bersifat struktural, menurut Baskara. Belum lagi, media sosial tempat generasi muda menggantungkan harap sebagai locus bagi diskursus yang bermutu dan demokratis justru tidak menawarkan pencerahan. Media sosial justru dipenuhi materi-materi yang justru membenamkan tingkat kecerdasan. Media sosial tidak menawarkan pencerahan dan kedalaman. Ryan Holiday, dengan mekanisme algoritma dan tarikan kapital, justru separuh menghujat dengan keras bahwa manipulator terbesar bagi media adalah media itu sendiri! (Marmion, 2018:188) Media, termasuk di dalamnya media sosial, justru membangun kamar gema (echo chamber) yang justru menepikan keterbukaan dan kemungkinan membangun jaring-jaring diskursus dan aksi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, lebih membawa harapan.
Baik Gita Wirjawan dan Baskara Putra melihat bahwa penegakan hukum menjadi keharusan yang perlu diusahakan. Untuk itulah pendidikan dan literasi menjadi fundamental. “Literasi bukan hanya soal membaca,” sebut Gita. “Literasi itu soal membaca, memahami, dan memitigasi risiko. Dengan literasi, kita perlu menafsir dan me-manage risiko,” lanjutnya. Peluang lain yang ditawarkan dalam diskusi ini adalah kemampuan bercerita. Kemampuan inilah yang membuat keresahan yang dialami generasi masa kini didengar, bukan hanya oleh masyarakat setempat bahkan oleh masyarakat global. Gita menegaskan bahwa narasi yang dibawakan Baskara melalui lagu-lagunya akan menyentuh sisi kognitif sekaligus afektif orang banyak.
Merawat makna merayakan 17 Agustus-an
Setelah mencecap visi gelap Baskara Putra, kita mungkin merasa bahwa apakah benar jika saat ini kita benar-benar telah mencecap kemerdekaan. Barangkali, memang betul bahwa kita tidak lagi dikejar-kejar tentara kolonial saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya seraya mengibarkan Sang Merah Putih. Memang betul, kepada kita tidak akan lagi dituntut upeti dalam kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa)yang ditetapkan Gubernur Jendral Belanda. Benar bahwa kita tidak ada lagi orang Jepang bersenjata katana yang membuat kita mengerjakan jalan dengan paksa, yang disebut romusha.
Sejak Jumat, 17 Agustus 1945, kita tidak lagi dikejar-kejar oleh iblis bernama penjajahan. Akan tetapi, bukankah iblis memiliki banyak wajah, bentuk, dan rupa? Bukankah sudah kodratnya iblis akan terus merongrong jiwa manusia hingga jatuh pada penderitaan dan penjajahan dewasa ini layaknya iblis yang lincah beralih rupa? Lalu, jika demikian halnya, adakah makna mengucap selamat dan merayakan pesta 17 Agustus-an?
Merenung tentang ini, mau atau tidak, kita perlu bertanya pada Driyarkara—pemikir yang disebut di awal tulisan. Kata Driyarkara, manusia adalah makhluk yang melampaui waktu. Apa artinya? Tidak lain adalah manusia mempunyai kesadaran akan waktu. Setidak-tidaknya, kesadaran akan waktu yang dimiliki manusia jauh lebih canggih daripada, katakanlah, kukang. Buktinya, kukang tidak pernah merayakan 17 Agustus-an, bukan? Artinya, bagi seekor kukang, kemarin, hari ini, dan esok hari tidak benar-benar berbeda.
Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan waktu. Manusia bisa memberi makna pada waktu yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Maka, manusia memiliki kesadaran atas dua hal termasuk paling mendasar pada kemanusiaannya: harapan dan ancaman. Pada dasarnya inilah paradoks kemanusiaan. Dengan harapan, manusia merajut asa untuk meraih kebahagiaan. Namun, pada saat yang bersamaan, dalam harapan selalu tersimpan ancaman. Oleh karena itulah, manusia merasa khawatir bahwa dirinya selalu berada dalam kemungkinan untuk tergelincir dari keadaan bahagia menjadi tidak bahagia.
Mengingat situasi yang sedemikian paradoksal, bukankah lebih baik dan lebih rasional untuk kita merayakan dan saling mengucapkan selamat pada 17 Agustus? Maka, segala komodifikasi kaum kapitalis dalam rupa potongan harga dan cashback pada 17 Agustus menjadi sangat rasional dan masuk akal. Kita—manusia fana ini—adalah makhluk yang membutuhkan perayaan. Kita butuh mengucap “selamat” untuk sekadar menikmati ke-seketika-an, melayangkan harap, dan melambungkan doa agar di masa mendatang, sebagai sebuah bangsa—masyarakat yang diimajinasi, sebagaimana Ben Anderson mencandra—kita akan menjalani masa yang membahagiakan.
Namun demikian, layak kita ingat bahwa situasi lain pun disediakan Baskara dalam lirik lagunya, Untuk Apa?
Mengejar mimpi sampai tak punya rasa/ Mengejar mimpi sampai lupa keluarga/ Mengejar mimpi lupa dunia nyata/ Mengejar mimpi tapi tidak bersama// Cepat namun sendiri, untuk apa?/ Bersama tapi meracuni, untuk apa?