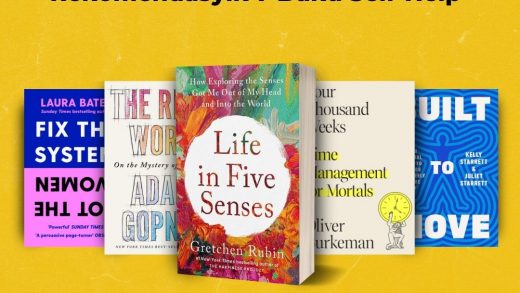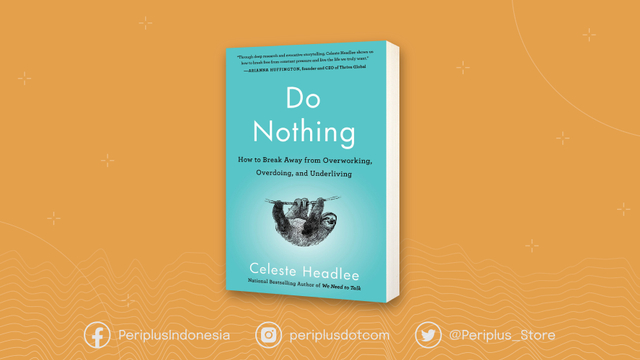
Judul: Do Nothing: How to Break Away from Overworking, Overdoing, and Underliving
Penulis: Celeste Headlee
ISBN: 9781984824752
Tahun : 2020
Halaman : 268 hlm.
Membaca Do Nothing
Membaca dan menikmati Do Nothing (2020), impresi pertama yang muncul bisa jadi terangkum dalam sebuah pertanyaan nakal, “Apakah ini buku tentang spiritualitas klumbrak-klumbruk?” Dalam bahasa Jawa kontemporer, klumbrak-klumbruk menggambarkan tumpukan pakaian yang belum tercuci, mangkrak di sudut ruang, di dalam mesin cuci, atau di samping lemari pakaian dan di balik daun pintu. Situasi pakaian yang bertumpuk tak teratur mau menggambarkan ulah manusia yang memilih rebahan melulu, kehilangan bergairah hidup, dan lemas terkulai. Apalagi, ditambah ilustrasi seekor kungkang (sloth) bergantung pada dahan. Mayoritas mengamini kungkang yang senyum wajahnya menggemaskan ini sebagai hewan lamban, mager, dan tidak energik. Makin sempurnalah pertanyaan di atas!
Secara tegas, Do Nothing ditujukan bagi para pekerja yang lelah, bergumul dengan keluh, dan berselimut angan untuk rehat. Celeste mengajak kita untuk menarik diri lalu mengambil jarak terhadap rutinitas bekerja. Dia membuat pembaca berefleksi terhadap realitas tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa dilakukan saat ini adalah panduan tepat untuk menyelam lebih dalam di lautan kata-kata pengarang buku laris manis, We Need to Talk (2017) ini.
Penulis membuka tulisannya dengan sangat realistis-tragis. Demikian tulisnya, “Kita membalas surel pekerjaan pada malam Senin. Kita membaca artikel tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak untuk bisa lebih produktif. Kita memangkas foto dan menggunakan filter sebelum diunggah di media sosial agar ‘diterima’. Kita hanya membaca dua paragraf awal sebuah tulisan untuk mencari mana yang menarik karena kita ‘tidak punya waktu’ untuk membaca semuanya. Kita terlampau banyak bekerja dan penuh tekanan, melulu tidak puas, dan berusaha mencapai standar yang makin tinggi. Kita adalah anggota dari ‘pemuja efisiensi’ dan kita membunuh diri sendiri dengan produktivitas.” (h. ix)
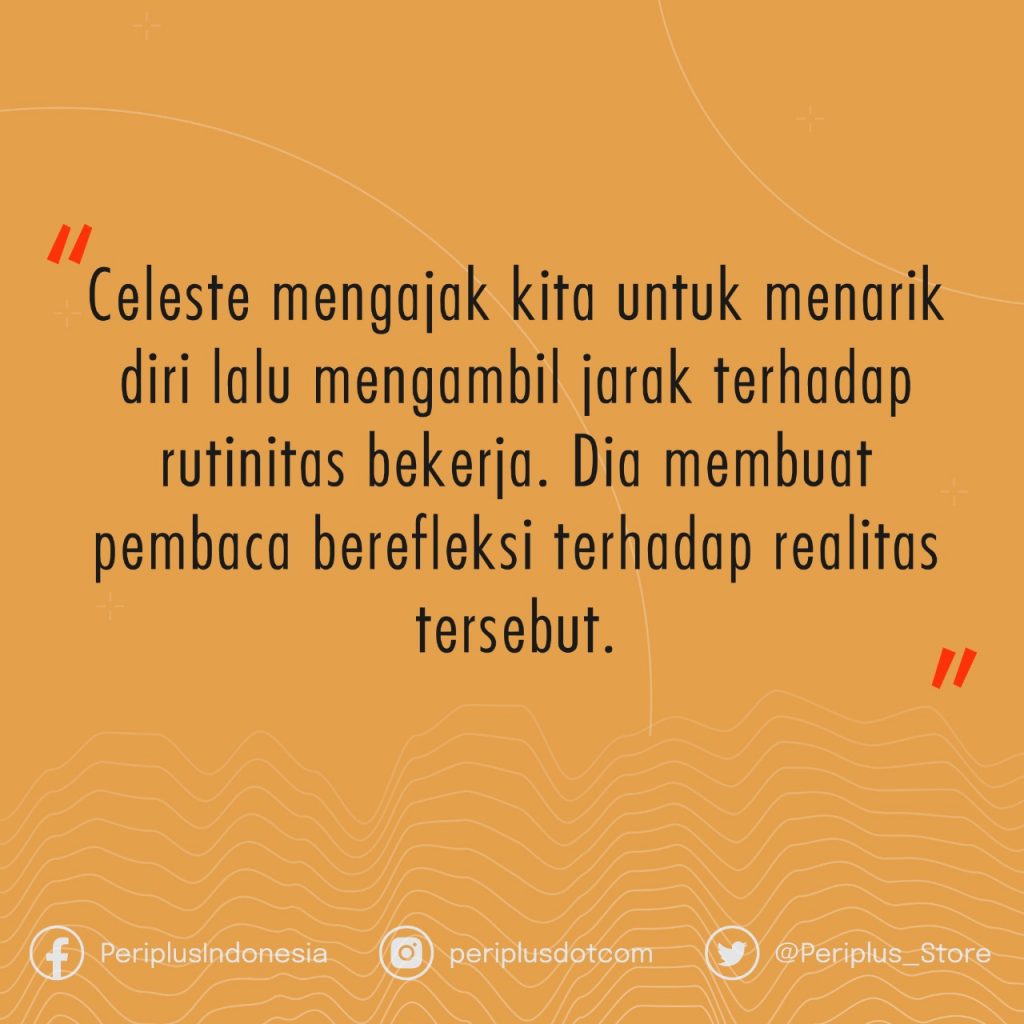
Pemujaan efisiensi
Celeste mengajak kita untuk menyadari perubahan paradigma pekerjaan dalam metamorfosis kata. Sekitar tahun 1600, kata punctuality dipadankan dengan “ketepatan”. Kemudian, seputar tahun 1777, orang mulai mengartikannya sebagai “tepat waktu”. Selama berabad-abad, efisiensi dimaknai sebagai kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Asal katanya adalah efficere, dalam Bahasa Latin bermakna “menyelesaikan”. Kemudian, di tahun 1780-an, sinonim efisiensi adalah kerja dengan produktif dan tahun 1850 ada artikel yang memuat kata efisiensi dengan menjabarkannya sebagai “perbandingan antara hasil pekerjaan dengan energi yang dikeluarkan”. Menggunakan waktu dengan baik mulai diartikan sebagai waktu yang digunakan untuk menghasilkan uang. (h. 25)
Revolusi industri berperan bagi perubahan makna yang besar untuk aktivitas bekerja, baik secara bentuk maupun secara esensinya. Penemuan mesin uap oleh James Watt adalah pemantik meletusnya Revolusi Industri pada abad ke-18 di Inggris. Pada masa ini, lahirlah istilah waktu adalah uang. Makin lama mesin-mesin beroperasi, maka makin banyak produksi dan uang yang dihasilkan pemilik pabrik. Pekerja pun tidak lagi diupah berdasar pekerjaannya, namun berdasar jumlah jam kerja. The Cult of Efficiency (Pemujaan Efisiensi) ini bermula di Inggris kemudian menyebar ke seluruh sudut dunia.
Dewasa ini, pemujaan terhadap efisiensi juga masih tampak pada sikap yang menganggap makin sibuk diri kita, maka kita makin baik. Aktivitas kerja lembur yang tidak terkontrol bisa jadi indikasi kalau kita justru jatuh pada aktivisme belaka. Fenomena ini ditengarai imbas dari mental revolusi industri 1.0 ketika jam kerja menjadi tolok ukur paten. Para pekerja dibayar berdasar jumlah jam kerja. Sehingga, kondisi ini membuat mereka yang menikmati waktu luang dianggap “bersalah dan berdosa”.
Efek kupu-kupu
Oleh karena itu, perlulah kita menarik diri barang sekejap untuk menimbang kembali kondisi dan produktivitas kita terkait jam kerja ini. Bisa jadi, secara tidak sadar, pola dan ritme kerja kita adalah butterfly effect dalam pemikiran Ben Franklin dan Frederick Douglass mengenai American Dream. Celeste menjelaskannya demikian, “Seseorang mencapai kesuksesan dikarenakan darah, keringat, dan air mata. Sebaliknya, seseorang yang tidak sukses biasanya karena tidak bekerja dengan cukup keras.” (h. 35)
Lemburan bisa diselisik dari alasan terjadinya aktivitas di luar jam kerja itu. Beberapa pertanyaan mengemuka. Mengapa harus lembur? Apakah 8 jam kerja sehari tidak cukup? Apakah fasilitas kerja kurang mendukung dalam waktu normal? Atau, apakah ada kegiatan yang kontrapoduktif dalam ekosistem kerja para karyawan? Apakah yang lembur itu lebih efektif dan efisien? Apakah imbas dari lemburan ini? Apa yang dikorbankan dan apa yang dicapai, sepadankah?
Di saat yang sama, tren bekerja di masa Revolusi Industri 4.0 memiliki cara pandang baru dalam memaknai produktivitas. Produktivitas diukur dari proses berpikir kreatif dan menciptakan suatu kebaruan. Berpikir kreatif sama saja bekerja. Arti produktif adalah keseimbangan antara kapasitas, energi, dan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Result oriented working, orang bilang saat ini. Pandangan ini menitikberatkan pada hasil dan produktivitas yang dicapai tanpa melihat jam kerja. Keberhasilan dan apresiasinya tidak didasarkan pada lemburan, bekerja di mana, atau perangkat apa yang digunakan. Sisi kreativitas lebih dihargai dalam memaknai produktivitas.
Waktu yang terpolusi
Josh Fear, Direktur Utama Institut Australia, menggunakan istilah waktu yang terpolusi (polluted time) untuk menggambarkan akibat dari pemujaan efisiensi yang berlebihan (h. 53). Fenomena ini diindikasi dari kegiatan mengerjakan pekerjaan ketika akhir pekan, siap sedia ditelepon 24 jam dalam sehari, membalas surel ketika sudah di rumah, atau bahkan masih memikirkan strategi dan keputusan bisnis serta pemecahan masalahnya ketika “seharusnya” tidak bekerja sama sekali. Tentu saja, ada anomali khusus untuk para pekerja di bidang tenaga kesehatan, pasukan pemadam kebakaran, atau mereka yang berada dalam dinas militer. Apabila ini terjadi pada pekerja sektor non-darurat, fenomena waktu yang terpolusi tidak dapat ditampik.
Kesadaran akan jam kerja yang menjadi tidak jelas ini juga dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Sudah barang tentu apabila teknologi menjadi sarana kerja utama. Alih-alih memberikan efisiensi dan efektifitas kerja, teknologi juga dapat menjadi “kambing hitam” pada fenomena waktu terpolusi ini. Kondisi ini justru membuat kita tidak dapat menempatkan diri secara sadar saat ini dan sekarang. Seakan-akan, setiap hari adalah hari kerja. Lebih parah lagi, waktu istirahat dan mimpi indah justru malah terintervensi oleh beban pekerjaan.
Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Los Angeles dan University of Toronto terhadap pekerja membuktikan bahwa ada kecenderungan emosi yang tidak stabil dalam diri pekerja. Para pekerja ini diajak masuk ke suatu ruangan untuk mendengarkan musik klasik. Ketika mendengarkan musik tersebut, para peneliti membacakan daftar pekerjaan mereka. Timbullah reaksi yang menarik untuk diperhatikan. Mereka yang memikirkan waktu adalah uang meminta ingin lebih cepat menyelesaikan lagu itu. Kesimpulannya, mereka tidak menikmati dan being present ketika tidak bekerja.
Pekerjaan pulang ke rumah
Batasan yang samar antara realitas kerja dan afeksi tidak lagi diindahkan. Seseorang menjadi gila kerja (workaholic) tanpa lagi sadar bahwa ada kebutuhan dan kewajiban lain yang harus ditunaikan. Kewajiban untuk hadir secara utuh dan penuh secara hati, raga, dan pikiran dalam lingkup keluarga tampaknya terpinggirkan oleh usaha membalas surel atasan atau klien. Memang, bekerja keras adalah hal yang baik untuk memperbaiki kondisi hidup kita yang tidak lagi hidup di taman Eden (h. 116). Yang harus dijadikan pegangan adalah kebahagiaan itu sendiri, ketika pekerjaan justru membawa kebahagiaan semu dan artifisial, maka kita perlu untuk memperbaikinya.
Hampir dua tahun belakangan ini, kita akrab dengan Work from Home (WfH). Pandemi menuntut kita untuk bekerja dari rumah supaya mengurangi risiko penularan virus. Namun, ada pula kecenderungan baru, yaitu work comes home, semua pekerjaan ikut pulang ke rumah. Ini membuat kita ragu menentukan waktu yang tepat kapan menutup laptop dan menarik selimut. Ujungnya, kadang kala, adalah peluapan emosi yang tidak sehat: marah kepada anak, istri, atau suami. Ketidakmampuan untuk memilah mana waktu bekerja dan mana waktu untuk “di rumah” membuat situasi makin runyam. Rumah kita menjadi kantor dan waktu luang kita tidak sungguh-sungguh luang (h. 93).
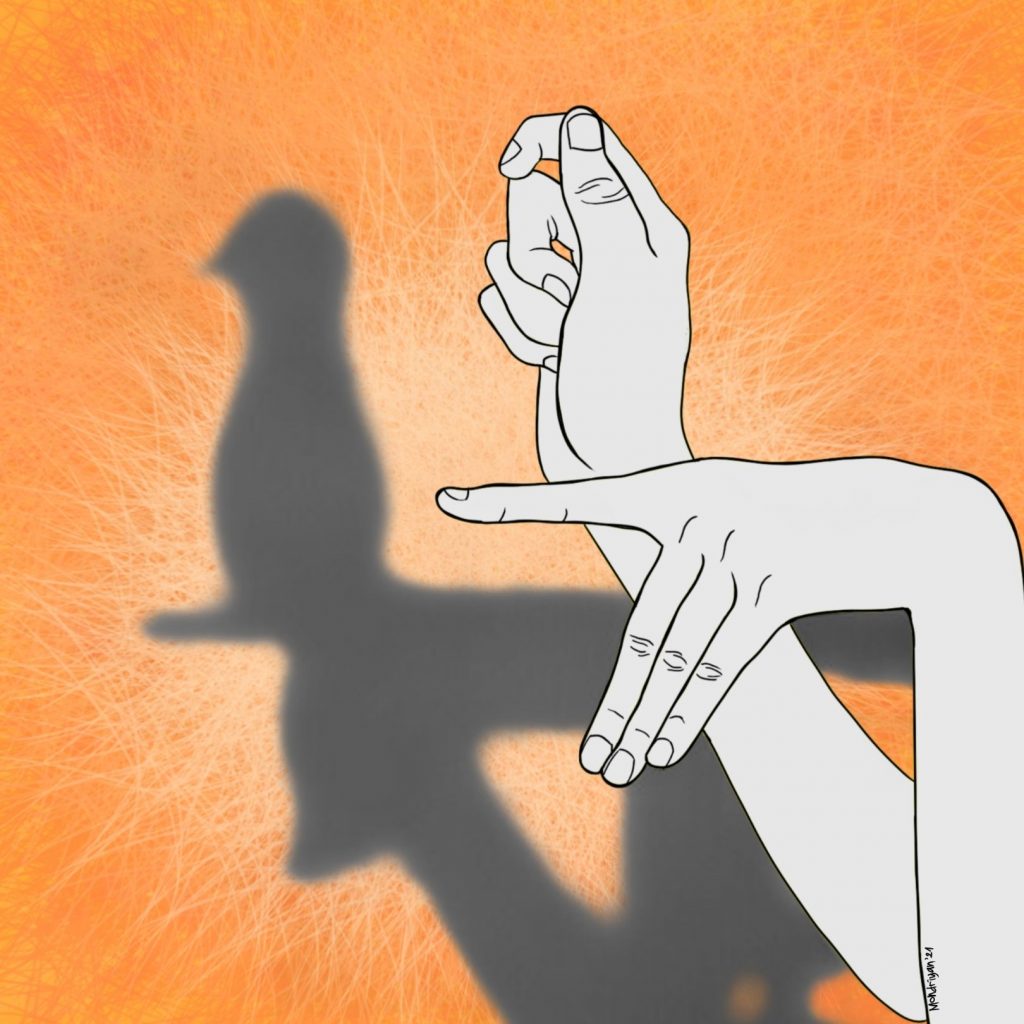
Meninggalkan pemujaan, kembali pada kehidupan
Pemujaan efisiensi menimbulkan waktu yang terpolusi dan membawa pekerjaan ke rumah menimbulkan gangguan hidup pribadi. Pertanyaan klasik, “Apakah kita hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup?” dirasakan masih aktual untuk digaungkan. Celeste mengajak kita untuk merefleksikan dan merestrukturasi makna panggilan hidup manusia. Berkaca atas fenomena di atas, kita ditantang untuk menjadi lebih seimbang. Bagian kedua Do Nothing menjabarkan mengenai bagaimana meninggalkan kultus efisiensi dengan beranjak dari habitus life-hack menuju life-back. (h. 173)
Ketika pekerjaan pulang ke rumah, sudah pasti afeksi relasi keluarga akan terkontaminasi. Imbas psikologis yang muncul adalah kondisi yang menuntut kita “seakan-akan” siap bekerja 24 jam dalam sehari. Keharmonisan menjadi tidak sehat. Sebab, bisa membuat kita lupa kapan bermain bersama anak, menonton film romantis bersama pasangan, atau sekadar kapan minum kopi ditemani pisang goreng bersama orang tua. Tetapi, jangan ambil tema obrolan tentang strategi bisnis saat makan malam bersama anak dan istri. Situasi pasti akan tidak nyaman bagi mereka. Aneh!
Kita harus berani bilang I’m done! Berhenti untuk urusan kantor ketika di rumah! Bila tidak, dunia tidak seimbang dan justru timpang tindih.
Ide yang ditawarkan adalah untuk membangun waktu berkualitas (quality time) dengan keluarga dan sahabat serta memberikan waktu pribadi (me time). Ketika jam kantor telah usai, kita diajak untuk meninggalkan gawai lalu kembali para realitas sosial kita. Melalui pembicaraan ringan dan bersenda gurau dengan teman, bermain bersama anak, atau bercurah hati kepada keluarga atau pasangan, maka hati, pikiran, dan jiwa kita akan disegarkan. Adalah benar kita perlu fokus untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi di masa depan. Hal itu sama pentingnya dengan memberikan waktu bersama komunitas dasar kita; teman dan keluarga. (h.216)
Waktu pribadi adalah saat kembali ke hobi dan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, orang bilang penghargaan untuk diri sendiri. Bentuknya bisa bermacam-macam, beberapa orang memilih pergi untuk kuliner makanan kegemarannya atau masuk ke dalam kamar, memutar musik, dan membaca buku. Ada pula yang memilih ke kedai kopi sambil bercengkerama dengan barista soal kopi single origin terbarunya. Ada juga yang memilih untuk mengambil kunci kendaraan dan pergi ke antah berantah. Terserah, intinya selamilah duniamu sendiri.
Memanusiakan kemanusiawian kita
Penulis mengajak kita untuk kembali mengacuhkan suara orang lain. Kurangnya rasa memiliki dan isolasi sosial cukup menghancurkan pikiran dan tubuh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki kehidupan sosial yang kaya membuat Anda lebih kecil kemungkinannya terkena kanker atau menderita serangan jantung. Orang-orang yang tergabung dalam suatu komunitas hidup lebih lama, mengalami lebih sedikit stres, dan lebih cenderung mengatakan bahwa hidup mereka bermakna. (h. 141)
Meluangkan waktu untuk orang lain adalah hal yang esensial. Kita tidak hidup dalam lingkup kerja selama 24 jam penuh. Berfokus pada efisiensi pekerjaan secara berlebihan justru memutuskan koneksi manusia. Ada waktu yang dikhususkan untuk bersosialisasi secara hangat dengan orang lain. Di sinilah, kita sebagai manusia berusaha mewujudkan kemanusiawian kita yang terkait denga kehadiran orang lain secara sempurna dan utuh. Pada akhirnya, seluruh usah dan hidup kita ini berasal dan akan kembali pada komunitas dasar: teman dan keluarga.
Komunitas adalah kata dalam berbagai bahasa yang bermakna penting dan itu adalah alasan utama keberadaan manusia. Habitus kerja kita itu terkait dengan kemampuan membangun komunitas. Bahasa itu esensial dan penting karena manusia tidak berjuang sendirian, namun dalam komunitas. (h. 135)
Hidup bersama orang dan bagi orang lain menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap memiliki rasa belas kasihan dan empati bagi orang lain. Usaha untuk pemenuhan kebutuhan diri melalui bekerja sangat perlu diimbangi dengan memenuhi kebutuhan diri akan kasih dan perhatian dari dan untuk orang lain. Inilah keseimbangan bagi kita, manusia.
Memperbaiki persepsi waktu
Banyak orang hari ini cenderung tidak merasa lelah ketika bermain dengan gawai dan media sosial. Media sosial seharusnya jadi kudapan saja, porsi cukup dua tiga kali saja, bukan menu utama dalam hidup sehari-hari. Bebaskan diri dari media sosial saat bekerja, mari melatih kesabaran untuk tidak buru-buru membuka media sosial ketika mendengar notifikasi agar kita tetap bekerja secara efisien dan penuh konsentrasi. Dari gawai pula kita belajar menjadi multitasking. Sayangnya, kita bukan mesin atau robot yang tidak memiliki perasaan, batas kekuatan, dan justru memiliki keterbatasan. Mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, justru menjadi indikasi bahwa benar “banyak fokus itu berarti tidak fokus”.
Ketika kita membisukan gawai, menutup surel, dan fokus menyelesaikan laporan yang kita susun untuk rapat selanjutnya, riset membutktikan kita akan selesai 40% lebih cepat. Kesalahan akan terminimalisir dan kita memiliki waktu untuk mengambil waktu rehat dan membiarkan pikiran kita rileks.
(h.210)
Oleh karena itu, kita perlu membuat daftar hal yang perlu dikerjakan (to do list) dan daftar hal yang tidak perlu dikerjakan (to do not list). Diri kita sendiri harus berani membuat transisi kapan memberikan diri secara utuh pada keluarga dan pada pekerjaan. Ini adalah soal berprinsip untuk berani berkata “tidak” membawa pulang pekerjaan ke rumah. Kita diajak untuk menyusun prioritas waktu kerja kita agar sungguh-sungguh efisien dan produktif. Sehingga, persepsi waktu yang sudah ada bagiannya masing-masing dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Celeste menegur dengan cukup keras sifat pengabdi uang yang hanya memikirkan menambah pundi kekayaan namun mengabaikan keluarga, kesehatan, dan sisi afektif.
Do Nothing
Do Nothing sudah barang tentu tidak mengakampanyekan gerakan untuk menjadi tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya. Do Nothing mengajak kita untuk tidak melakukan pekerjaan di saat waktu non-kerja. Tidak mengerjakan apa pun bukan berarti kita diajak untuk menganggur, leha-leha, dan menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya, semangat yang ditawarkan dalam Do Nothing memberi kesempatan kita untuk mengolah waktu untuk tidak masuk dalam kesibukan kerja melulu. Tarik nafas dan hembuskan.
Pada akhirnya, Celeste mengajak kita memulihkan energi dan mengisi ulang tangki emosi kita. Salah seorang rohaniwan kenalan saya pernah mengatakan begini, “Ketika kita makin sibuk, kita harus makin banyak mencari ruang hening dalam hati, lalu makin banyak pula berdoa.”